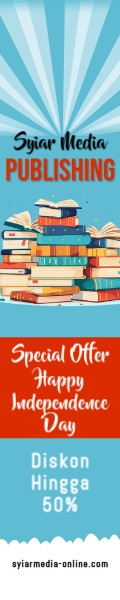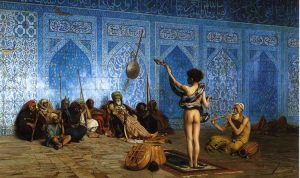Pendahuluan: Mengapa Etika Penulisan Ilmiah Itu Penting?
Etika penulisan ilmiah adalah fondasi kepercayaan publik terhadap sains. Tanpa etika, capaian riset mudah runtuh seperti bangunan tanpa pondasi: rapuh, berisik, dan berbahaya. Etika memastikan bahwa apa yang kita klaim dapat diverifikasi, diulang, dan dipertanggungjawabkan. Ia mengikat proses—dari perumusan pertanyaan riset, pengumpulan data, analisis, hingga pelaporan—agar transparan dan jujur. Buku klasik On Being a Scientist menekankan bahwa integritas bukan sekadar mematuhi aturan, tetapi menjunjung nilai—kejujuran, ketelitian, dan akuntabilitas—yang menjamin kemajuan ilmu sekaligus reputasi peneliti dan lembaganya. Pelanggaran etika bisa berujung pada penarikan artikel (retraction), kehilangan dana riset, dan bahkan sanksi institusional. Di sisi lain, etika yang kuat mempercepat kolaborasi dan sitasi, memudahkan replikasi, serta mendorong inovasi berbasis bukti. Etika juga melindungi pembaca: mereka berhak tahu asal-usul data, tingkat ketidakpastian, dan batas inferensi, alih-alih dikecoh oleh angka-angka “cantik” atau narasi bombastis. Praktik terkini menuntut transparansi lebih tinggi—misalnya, membuka data, kode, dan protokol sedapat mungkin—serta keterbukaan tentang konflik kepentingan finansial maupun nonfinansial. Di tengah ekosistem publikasi yang semakin kompleks—open access, pra-cetak, dan alat AI—memahami etika bukan lagi “tambahan”, melainkan prasyarat untuk layak terbit. Untuk menulis dengan etis, rujuklah standar internasional, panduan penerbit, dan literatur integritas ilmiah; jadikan kebiasaan berdasar bukti. Dengan begitu, naskah Anda bukan hanya “diterima”, tetapi juga memberi nilai yang tahan uji waktu.
Dampak Nyata Pelanggaran Etika bagi Karier dan Ilmu Pengetahuan
Pelanggaran etika berimplikasi jauh melampaui satu artikel. Ketika data dimanipulasi atau hasil ditulis menyesatkan, peneliti lain bisa menghabiskan waktu dan dana mengikuti jejak yang keliru. Analisis besar terhadap penarikan artikel menunjukkan bahwa banyak retraction bukan karena kesalahan jujur, melainkan karena bentuk-bentuk pelanggaran serius seperti fabrikasi, falsifikasi, atau plagiarisme. Penarikan semacam ini merusak kepercayaan, menghambat kemajuan, dan mencoreng reputasi penulis, laboratorium, dan jurnal yang menerbitkannya. Salah satu studi berpengaruh di PNAS menemukan bahwa mayoritas penarikan publikasi ilmiah terkait dugaan kesalahan etik, bukan sekadar error metodologis biasa—sebuah alarm keras bahwa integritas bukan jargon, melainkan garis pertahanan utama ilmu pengetahuan. Bagi karier, retraction dapat memicu audit, hilangnya kolaborasi, dan sulitnya memperoleh pendanaan. Secara sosial, dampaknya juga nyata: kebijakan publik dan praktik klinis yang bertumpu pada temuan cacat berpotensi menimbulkan kerugian. Artinya, setiap penulis memikul tanggung jawab ganda—pada komunitas ilmiah dan masyarakat. Di tengah tekanan “publish or perish”, berpegang pada etika adalah strategi jangka panjang: reputasi Anda adalah aset. Dengan mematuhi pedoman internasional (misalnya ICMJE, COPE) dan mengadopsi standar keterbukaan (TOP, FAIR), Anda menurunkan risiko bias, duplikasi, dan klaim berlebihan—serta meningkatkan keandalan naskah di mata editor dan reviewer.
Prinsip-Prinsip Dasar: Kejujuran, Transparansi, Keadilan
Tiga prinsip ini—kejujuran, transparansi, dan keadilan—adalah sumbu etika penulisan ilmiah. Kejujuran menuntut pelaporan apa adanya: tidak mengubah data, tidak memilih-milih hasil, dan tidak menulis klaim melebihi bukti. Transparansi berarti membuka metode, data, dan keputusan analitik sejauh memungkinkan, agar orang lain dapat menilai dan mengulang. Keadilan mencakup atribusi yang tepat (kredit untuk kontributor), pengungkapan konflik kepentingan, serta perlakuan setara pada kolaborator lintas institusi atau negara. Untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip ini, komunitas sains mengusung standar TOP Guidelines (Transparency and Openness Promotion)—kerangka modular yang mendorong keterbukaan data, kode, dan material, serta preregistrasi analisis. Di ranah data, FAIR Principles menuntun agar data dapat Findable, Accessible, Interoperable, dan Reusable—bukan hanya bagi manusia, tetapi juga mesin—sehingga keberulangan dan pemanfaatan ulang menjadi realistis. Ketiganya saling melengkapi: TOP memandu kebijakan jurnal dan praktik penulis; FAIR memandu pengelolaan data; sedangkan prinsip kejujuran dan keadilan memastikan bahwa keterbukaan tidak berubah menjadi “etalase” tanpa isi. Praktik konkret? Cantumkan data availability statement, unggah dataset dan kode di repositori tepercaya, jelaskan perangkat lunak/statistik yang digunakan, dan sertakan readme yang jelas. Jangan lupa, atribusi peran penulis (mis. dengan CRediT) membantu mencegah “gift authorship” dan memperjelas akuntabilitas. Pada akhirnya, etika bukan sekadar mematuhi checklist, melainkan kebiasaan berpikir: berasumsi bahwa pembaca cerdas, kritis, dan berhak menelusuri jejak kerja Anda secara menyeluruh.
TOP & FAIR: Standar Keterbukaan dan Manajemen Data
Bagaimana menerjemahkan transparansi ke dalam langkah nyata? Mulailah dari TOP Guidelines—standar yang diperkenalkan di Science—yang menawarkan delapan domain keterbukaan (sitasi, data, kode/material, transparansi analisis & desain, pra-registrasi, replikasi, dsb.) dengan level kepatuhan bertingkat. Banyak jurnal kini meminta checklist TOP saat submisi atau revisi, sehingga sejak awal penulis “dipaksa” merencanakan pengelolaan data dan bahan. Untuk data, pegang FAIR: berikan DOI, metadata standar, format terbuka, dan lisensi jelas untuk memungkinkan temuan Anda ditemukan, diakses, dipakai ulang, serta diintegrasikan lintas sistem. Prinsip ini memudahkan meta-analysis dan machine-actionability, relevan di era sains berbasis komputasi. Implementasi praktis mencakup memilih repositori tepercaya (mis. domain-specific atau generalist), menuliskan data dictionary, serta menyiapkan codebook dan workflow (mis. scripts untuk reproduksi analisis). Kualitas dokumentasi sama pentingnya dengan kualitas data—tanpa dokumentasi, data mudah salah tafsir. Beberapa jurnal memberikan badges untuk artikel dengan data/kode terbuka; ini bukan sekadar lencana, tetapi sinyal kuat pada pembaca bahwa klaim Anda siap diuji. Jika ada batasan (privasi, kerahasiaan, lisensi pihak ketiga), jelaskan secara spesifik, bukan sekadar “data available upon request”. Langkah-langkah ini meningkatkan kepercayaan reviewer dan editor—sering kali mempercepat proses evaluasi karena bukti keterlacakan tersedia. Jangan lupa, kebijakan pendana dan institusi kian mendorong keterbukaan; mengikuti TOP & FAIR bukan hanya etis tetapi strategis untuk kelangsungan riset Anda.
Orisinalitas, Plagiarisme, dan Text Recycling
Orisinalitas adalah nyawa tulisan ilmiah. Namun, orisinal bukan berarti “tanpa rujukan”—justru sebaliknya: argumen baru berdiri di atas pondasi literatur yang dikutip akurat dan jujur. Plagiarisme terjadi saat gagasan, data, atau kata-kata orang lain digunakan tanpa atribusi yang memadai. Bentuknya beragam: copy–paste mentah, parafrase terlalu dekat (hampir identik dengan sumber), hingga meminjam struktur argumen tanpa menyebutkan rujukan. Ada pula text recycling atau self-plagiarism: mengulang potongan teks sendiri dari publikasi sebelumnya tanpa transparansi. Topik ini makin hangat seiring meningkatnya tekanan publikasi dan hadirnya alat bantu penulisan. Kabar baiknya, komunitas ilmiah mulai membedakan antara pengulangan teks yang fungsional (misal, deskripsi metode standar) dan yang problematik (menyuguhkan “karya baru” padahal esensinya duplikasi). Riset terkini mengusulkan taksonomi dan kebijakan tekstual yang lebih bernuansa agar penulis punya pedoman yang jelas, bukan sekadar larangan. Intinya, orisinalitas bukan hanya soal kata-kata baru, melainkan kontribusi intelektual baru—baik dari segi data, analisis, sintesis teori, maupun interpretasi. Praktiknya: kutip ide orang lain secara eksplisit, gunakan tanda kutip untuk kutipan langsung yang pendek, dan saat perlu menulis ulang bagian metode yang identik, jelaskan sumber serta alasan pengulangan. Transparansi menyelamatkan Anda dari kecurigaan sekaligus menolong pembaca menelusuri konteks ilmiah dengan benar.
Batas Wajar Parafrase vs. Self-Plagiarism
Sampai batas mana parafrase dianggap etis? Parafrase yang etis mengubah struktur kalimat dan memilih diksi baru sambil mempertahankan makna, serta menyebut sumber. Jika Anda mengganti kata tetapi mempertahankan struktur dan alur argumen secara identik tanpa sitasi, itu tetap plagiarisme. Untuk self-plagiarism, banyak jurnal mengizinkan pengulangan teks terbatas di bagian metode—asal transparan dan tidak menyesatkan novelty. Proyek Text Recycling menekankan perlunya istilah dan pedoman yang jelas, karena tidak semua pengulangan setara: ada developmental, generative, hingga ethical text recycling yang diterima dalam batas tertentu (mis. deskripsi instrumen yang persis sama). Namun mengulang bagian pendahuluan, hasil, dan pembahasan secara substansial dari publikasi sebelumnya—tanpa sitasi dan penjelasan—umumnya dianggap pelanggaran. Strateginya: (1) tandai bagian yang Anda ambil ulang; (2) rujuk publikasi asalnya; (3) jelaskan apa yang benar-benar baru di naskah terkini. Jika masih ragu, cek pedoman jurnal dan kebijakan penerbit. Hindari mengandalkan “skor” alat pendeteksi sebagai satu-satunya tolok ukur; yang utama adalah niat dan konteks ilmiah. Terakhir, ingat bahwa redundant publication (membelah satu studi menjadi beberapa artikel kecil/salami slicing) bukan solusi etis untuk mengejar jumlah artikel—kita akan membahasnya tersendiri. Etosnya tetap sama: jujur pada pembaca tentang apa yang baru, apa yang diulang, dan mengapa.
Penulis & Kontributor: Kriteria, Urutan, dan CRediT
Salah satu sumber friksi paling umum dalam penulisan ilmiah adalah kepengarangan: siapa layak menjadi penulis, urutannya bagaimana, dan apa tanggung jawab setiap orang. ICMJE menetapkan empat kriteria penulis yang menuntut kontribusi substansial pada desain/analisis/interpretasi, keterlibatan dalam penulisan atau telaah kritis, persetujuan final, dan akuntabilitas atas seluruh isi. Mereka yang tidak memenuhi keempatnya—misalnya hanya menyediakan dana, fasilitas, atau proofreading—seharusnya diakui dalam bagian acknowledgments, bukan di byline. Urutan penulis hendaknya disepakati sejak awal proyek dan ditinjau sebelum submisi; tak ada satu sistem baku, tetapi kejelasan dan persetujuan semua pihak adalah kuncinya. Untuk meningkatkan keadilan dan akuntabilitas, banyak jurnal mengadopsi CRediT (Contributor Roles Taxonomy), yakni 14 kategori peran (mis. Conceptualization, Data curation, Formal analysis, Investigation, Methodology, Project administration, Software, Supervision, Validation, Visualization, Writing—original draft, Writing—review & editing, dll.). Dengan CRediT, pembaca dapat melihat siapa melakukan apa, dan sengketa kepengarangan bisa ditekan karena kontribusi tertulis secara spesifik. Penerapan CRediT tidak mengubah kriteria kelayakan penulis; ia melengkapi, bukan mengganti, pedoman ICMJE. Praktik baik: dokumentasikan peran tiap anggota tim secara living document, perbarui bila ada perubahan, dan cantumkan secara resmi saat submisi. Untuk kolaborasi besar lintas institusi/negara, kebiasaan ini menyelamatkan banyak waktu dan potensi konflik
Kriteria ICMJE & Peran CRediT (14 Role)
Mari konkretkan. ICMJE menegaskan bahwa semua penulis harus memenuhi keempat kriteria—bukan salah dua atau tiga. Konsekuensinya, praktik “gift authorship” (mencantumkan nama demi sopan santun atau jabatan) atau “ghost authorship” (kontributor substansial yang tidak dicantumkan) jelas melanggar etika. Di saat yang sama, CRediT membantu menjabarkan kontribusi sehingga publik tahu siapa merancang metodologi, siapa menulis draf awal, siapa melakukan analisis, dan siapa mengurusi visualisasi. Menariknya, CRediT juga memungkinkan penandaan derajat kontribusi (mis. lead, equal, atau supporting)—mendorong transparansi yang lebih tajam dalam publikasi multi-penulis. Penerbit besar (Elsevier, Wiley, PLOS, OUP, AGU) telah mengadopsinya luas; banyak jurnal meminta author contribution statement sebagai syarat. Bagi penulis muda, ini kabar baik: kontribusi yang sering “tidak terlihat” (mis. data curation atau software) kini diakui. Ingat pula pembaruan penting: ICMJE secara eksplisit menyatakan bahwa teknologi AI/LLM tidak dapat menjadi penulis dan wajib diungkap jika digunakan, baik untuk penulisan, analisis, pengumpulan data, atau pembuatan gambar. Pengungkapan dilakukan di acknowledgments atau metode, dengan penulis manusia memikul tanggung jawab penuh atas akurasi dan orisinalitas materi yang dihasilkan. Semua ini kembali ke nilai inti: siapa pun yang menerima kredit harus siap memikul tanggung jawab ilmiahnya.
Data & Metode: Replikasi, Berbagi, dan Kualitas Pelaporan
Bagian metode sering dipandang sebagai “rutin”, padahal di sinilah reputasi replikasi ditentukan. Metode yang detail, transparan, dan dapat diikuti ulang adalah tiket agar temuan Anda hidup melampaui satu publikasi. Terapkan prinsip FAIR pada data (DOI, metadata standar, format terbuka) dan ikuti standar pelaporan yang relevan (mis. CONSORT, PRISMA, STROBE, ARRIVE, dan seterusnya—tergantung bidang). Di domain psikologi dan ilmu perilaku, banyak jurnal mengadopsi TOP Guidelines, mendorong penulis mempublikasikan data dan kode, atau setidaknya availability statement yang jelas. Beberapa jurnal meminta preregistration desain/analisis, mengurangi godaan p-hacking atau HARKing. Praktik bagus lain: sertakan informasi perangkat lunak (versi, paket, seed acak), lingkungan komputasi (mis. kontainer), serta readme yang menjelaskan struktur folder proyek. Untuk data sensitif, gunakan pendekatan controlled access (mis. de-identifikasi, Data Use Agreement) dan jelaskan batasannya. Pelaporan yang teliti bukan semata memenuhi tuntutan reviewer; itu cara Anda menghormati pembaca dengan memberi “peta jalur” yang bisa diikuti. Bonusnya, penelitian yang dapat direplikasi cenderung lebih sering disitasi. Jika repositori domain-spesifik tidak tersedia, gunakan repositori generalist tepercaya. Hindari “data upon reasonable request” jika sebenarnya data tak siap atau tidak terdokumentasi; itu justru menurunkan kredibilitas. Singkatnya, lakukan dari awal: rancang workflow yang bisa dipublikasikan—bukan mendadak merapikan di akhir.
Checklist Pelaporan & Repositori: Dari Niat Baik ke Bukti
Ubah niat baik menjadi kebiasaan sistematis dengan checklist. Mulailah dari project charter yang menyebut: tujuan, hipotesis, rencana analisis, pembagian peran (CRediT), kebijakan data (FAIR), dan rencana publikasi. Saat menulis, gunakan daftar periksa pelaporan yang sesuai (CONSORT/PRISMA/ARRIVE, dll.) dan lampirkan di supplement. Di tahap submisi, banyak jurnal kini meminta TOP checklist—jawaban jujur lebih dihargai daripada klaim terbuka yang tidak bisa dipenuhi. Untuk repositori, utamakan yang tepercaya: menyediakan DOI, versi, dan kebijakan preservasi jangka panjang. Cantumkan lisensi (mis. CC BY untuk data non-sensitif) dan berikan data dictionary serta codebook agar dataset benar-benar dapat digunakan ulang. Jika ada pembatasan (privasi pasien, rahasia dagang), jelaskan secara spesifik mengapa dan bagaimana pembaca tetap dapat memverifikasi klaim (mis. akses terbatas via komite data). Beberapa jurnal membubuhkan open data/material badges untuk menghargai keterbukaan; manfaatkan ini sebagai insentif reputasi. Ingat, transparansi bukan lomba unggah sebanyak-banyaknya, melainkan menyediakan materi yang diperlukan untuk menguji klaim naskah. Akhirnya, dokumentasikan keputusan sepanjang proyek—audit trail akan memudahkan Anda menjawab pertanyaan reviewer/editor dan mengurangi kebingungan saat tim berubah personel. Dengan disiplin semacam ini, bagian metode dan lampiran Anda akan terasa “bernapas”: logis, lengkap, dan mudah diikuti, persis seperti yang diidealkan TOP & FAIR.
Peer Review yang Etis: Tanggung Jawab Penulis, Reviewer, dan Editor
Peer review adalah tulang punggung publikasi ilmiah—saringan yang memastikan naskah layak terbit, bebas kesalahan fatal, dan memiliki kontribusi berarti. Namun, peer review hanya seefektif integritas para aktornya: penulis, reviewer, dan editor. Penulis berkewajiban menyampaikan naskah yang jujur, lengkap, dan transparan, serta menanggapi komentar reviewer dengan sikap konstruktif, bukan defensif. Reviewer harus menilai naskah secara objektif, berdasarkan bukti, bukan kepentingan pribadi atau persaingan. Mereka wajib menjaga kerahasiaan konten, menghindari konflik kepentingan, dan tidak menggunakan ide/data dalam naskah yang mereka tinjau untuk kepentingan sendiri. Editor, di sisi lain, adalah penentu kebijakan: mereka bertanggung jawab memilih reviewer yang kompeten, menimbang masukan secara seimbang, dan membuat keputusan adil tanpa bias institusional, geografis, atau ideologis. Organisasi seperti COPE (Committee on Publication Ethics) telah menyusun pedoman rinci tentang peran dan kewajiban setiap pihak. Model review juga bervariasi: single-blind, double-blind, open review, hingga post-publication review. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan, tetapi intinya sama: menjaga kredibilitas naskah melalui evaluasi sejawat yang jujur. Penulis juga punya kewajiban etis saat memilih jurnal—jangan “shotgun submission” (mengirim naskah ke banyak jurnal sekaligus). Peer review sejatinya adalah percakapan akademik, bukan perang ego. Dengan menjalaninya secara etis, semua pihak berkontribusi pada kualitas ilmu dan menjaga kepercayaan publik.
Kerahasiaan, COI, dan Etika Menanggapi Review
Salah satu aspek paling sensitif dari peer review adalah kerahasiaan. Reviewer tidak boleh membagikan naskah, ide, atau data kepada pihak lain tanpa izin editor. Mereka juga tidak boleh memanfaatkan informasi dari naskah untuk keuntungan pribadi, misalnya mendahului publikasi ide serupa. Konflik kepentingan (COI)—baik finansial, profesional, maupun pribadi—harus diungkap sebelum menerima tugas review. Jika reviewer merasa tidak kompeten di bidang tertentu atau tidak dapat memberikan penilaian objektif, etisnya menolak. Dari sisi penulis, etika muncul saat menanggapi komentar reviewer. Respons sebaiknya disusun dengan sopan, terstruktur, dan berbasis bukti. Hindari nada emosional atau argumen ad hominem. Jika menolak saran reviewer, berikan alasan ilmiah yang kuat, bukan sekadar opini. Beberapa jurnal kini menerapkan transparent peer review, di mana laporan review dipublikasikan bersama artikel; hal ini meningkatkan akuntabilitas reviewer sekaligus memberi pembaca wawasan tentang proses seleksi. Model ini menuntut standar etika yang lebih tinggi karena semua pihak tahu komentarnya bisa dilihat publik. Singkatnya, etika peer review bukan hanya soal aturan, melainkan cermin budaya akademik: apakah kita menghargai karya orang lain seperti kita ingin karya kita diperlakukan.
Duplikasi, Redundant Publication & Salami Slicing
Dalam dunia riset yang kompetitif, ada godaan untuk “memperbanyak” publikasi dari satu dataset—praktik yang dikenal sebagai redundant publication atau salami slicing. Redundant publication adalah publikasi ulang artikel yang secara substansial sama, biasanya tanpa rujukan silang yang memadai. Salami slicing, sebaliknya, membagi satu studi besar menjadi artikel-artikel kecil yang sebenarnya bisa digabung. Kedua praktik ini menimbulkan masalah serius: mengacaukan meta-analisis, menggandakan literatur tanpa kontribusi baru, dan menipu pembaca/editor dengan ilusi produktivitas. COPE menyebutkan bahwa publikasi ganda yang tidak transparan adalah bentuk pelanggaran etika. Ada pengecualian: misalnya publikasi ulang dengan tujuan menjangkau audiens berbeda (mis. terjemahan), asal jelas diungkapkan dan disetujui editor. Redundansi yang tidak diakui dapat berujung pada penarikan artikel dan rusaknya reputasi. Bagi penulis, strategi yang benar adalah merencanakan publikasi sejak awal proyek: mana pertanyaan riset utama yang layak satu artikel penuh, mana hasil sekunder yang pantas menjadi laporan tambahan. Transparansi sangat penting—jika ada overlap dengan publikasi sebelumnya, cantumkan dengan jelas. Editor menghargai kejujuran lebih daripada produktivitas semu. Dengan demikian, kualitas lebih diutamakan dibanding kuantitas.
Studi Kasus dan Sinyal Peringatan
Beberapa studi kasus menunjukkan betapa berbahayanya duplikasi. Misalnya, analisis terhadap publikasi klinis menemukan bahwa salami slicing dapat menggandakan bobot studi kecil dalam meta-analisis, sehingga hasil sintesis menjadi bias. Salah satu sinyal peringatan bagi editor adalah kemiripan metodologi, sampel, atau hasil dengan publikasi penulis sebelumnya—tetapi dengan framing berbeda. Misalnya, data dari 100 pasien dibagi menjadi tiga artikel: satu fokus pada variabel A, satu pada variabel B, satu lagi pada variabel C—padahal ketiganya berasal dari satu studi tunggal tanpa pengakuan. Kasus lain adalah publikasi ulang “teks” yang sama dengan minor perubahan judul atau urutan penulis. Praktik ini membebani sistem peer review, memperlambat proses editorial, dan bisa menipu pembaca yang mengira itu studi independen. Solusi praktis: buat publication plan sejak awal, diskusikan dengan tim, dan gunakan preprint untuk hasil parsial yang memang relevan, bukan memaksa setiap fragmen jadi artikel jurnal. Jika ada keraguan, komunikasikan dengan editor; banyak jurnal menghargai keterbukaan dan bersedia menilai kasus per kasus. Etika publikasi bukan hanya soal menghindari sanksi, melainkan melindungi integritas bukti ilmiah agar tidak “berlapis-lapis asap” yang membingungkan.
Manipulasi Data & Gambar, serta Retraction
Manipulasi data dan gambar adalah pelanggaran etika paling serius, karena merusak fondasi kepercayaan pada ilmu. Bentuknya beragam: fabrication (membuat data fiktif), falsification (mengubah/menghapus data agar sesuai hipotesis), dan manipulasi gambar (memotong, menempel, atau memperkuat sinyal secara berlebihan tanpa penjelasan). Banyak kasus retraction di jurnal besar disebabkan oleh manipulasi gambar, terutama di bidang biomedis. COPE menekankan bahwa setiap modifikasi gambar harus dijelaskan di metode dan tidak boleh mengubah interpretasi ilmiah. Misalnya, penyesuaian kontras/brightness masih diperbolehkan asal diterapkan pada seluruh gambar dan dicatat dengan jelas. Retraction menjadi jalan terakhir jika pelanggaran terbukti substansial dan mengancam integritas literatur. Proses ini bukan hukuman semata, melainkan mekanisme koreksi ilmiah. Sayangnya, stigma retraction masih besar, padahal dalam beberapa kasus ia merupakan bentuk tanggung jawab penulis atau jurnal untuk melindungi komunitas. Agar terhindar dari risiko, penulis sebaiknya menyimpan raw data, mendokumentasikan proses analisis, dan menggunakan perangkat lunak audit trail. Beberapa jurnal kini mewajibkan unggahan data mentah sebagai bahan verifikasi. Intinya: data tidak boleh “dipermak” untuk tampak indah; biarkan ia berbicara apa adanya.
Bentuk-Bentuk “Beautification” yang Berisiko
Di era perangkat lunak canggih, godaan untuk memperindah hasil riset besar. Grafik bisa dibuat lebih “dramatis”, gambar mikroskop bisa diperjelas berlebihan, atau kurva bisa dipangkas agar terlihat “rapi”. Inilah yang disebut “beautification”—batas tipis antara penyajian visual yang sah dan manipulasi. COPE memberi panduan: modifikasi diperbolehkan jika tidak mengubah makna ilmiah, dan harus dilaporkan. Contoh etis: menyesuaikan kecerahan seluruh citra untuk keterbacaan. Contoh tidak etis: menghapus pita yang tidak sesuai hipotesis dari gel elektrofloresis. Retraction Watch mencatat bahwa banyak kasus manipulasi gambar terbongkar setelah publikasi melalui image integrity software atau deteksi komunitas. Untuk mencegah risiko, biasakan menyimpan file mentah, buat log perubahan, dan gunakan open lab notebook. Ingat, integritas visual sama pentingnya dengan integritas teks. Lebih baik gambar “kurang estetik” tetapi asli, daripada visual menawan tapi menyesatkan. Selain itu, banyak penerbit kini mewajibkan pernyataan tentang pemrosesan gambar. Transparansi kecil seperti ini adalah perisai besar bagi reputasi Anda. Etika bukan hanya di teks, tapi juga di visual yang menjadi wajah data Anda.
Memilih Jurnal & Fenomena Predatory Publishing
Memilih jurnal bukan sekadar soal impact factor atau kecepatan terbit. Pilihan yang etis melibatkan pertimbangan: apakah jurnal menerapkan peer review yang kredibel, terindeks di basis data bereputasi, serta mengikuti pedoman etika publikasi internasional. Di sisi lain, fenomena predatory publishing makin marak: jurnal yang mengklaim internasional, memungut biaya tinggi, tetapi tanpa peer review yang layak. Karakteristiknya: email spam undangan publikasi, situs web minim informasi editorial, janji terbit sangat cepat, dan editor/panel ilmiah yang mencurigakan (sering mencatut nama akademisi tanpa izin). Publikasi di jurnal predator merugikan penulis karena naskah sering tidak diakui dalam evaluasi akademik, dan reputasi bisa tercoreng. Cara menghindari: periksa di DOAJ untuk jurnal open access, cek indeksasi di Scopus/WoS, atau gunakan Think.Check.Submit.—sebuah checklist sederhana untuk menilai kredibilitas jurnal. Lembaga besar seperti COPE, OASPA, dan WAME juga punya daftar anggota jurnal/penerbit yang berkomitmen pada etika. Memilih jurnal etis berarti melindungi karya Anda agar terarsipkan secara sahih, diakses komunitas yang tepat, dan diakui dalam karier akademik. Jangan terkecoh oleh “impact factor” palsu atau label internasional yang tidak jelas sumbernya. Etika publikasi juga berarti bijak memilih rumah bagi riset Anda.
Red Flags & Cara Verifikasi
Bagaimana mengenali jurnal predator? Ada sejumlah red flags yang bisa diwaspadai: (1) janji terbit sangat cepat (misalnya <1 minggu), (2) biaya publikasi (APC) tidak transparan, (3) kontak editorial hanya berupa email umum (Gmail/Yahoo), (4) jurnal mengklaim terindeks padahal tidak ada di database resmi, (5) artikel yang terbit berkualitas buruk, banyak kesalahan tata bahasa, atau tidak relevan dengan scope, (6) nama jurnal mirip dengan jurnal bereputasi (misalnya Nature Journal of Science), (7) proses peer review tidak jelas atau bahkan tidak ada. Untuk verifikasi, gunakan Think.Check.Submit.: periksa dewan editorial (apakah kredibel?), lihat apakah jurnal terdaftar di DOAJ, apakah penerbit anggota COPE, dan cek apakah jurnal benar-benar muncul di Scopus/Web of Science. Alat bantu seperti Cabells’ Predatory Reports juga berguna untuk menilai reputasi jurnal. Jika ragu, tanyakan pada mentor atau pustakawan riset. Mengirim ke jurnal predator bukan hanya membuang dana, tetapi juga berisiko mengunci artikel di outlet yang tidak diakui. Pilihan bijak adalah memprioritaskan jurnal dengan reputasi baik di bidang Anda, meskipun prosesnya lebih ketat dan memakan waktu. Akhirnya, etika publikasi dimulai sejak pemilihan jurnal—karena tempat Anda menaruh riset ikut menentukan bagaimana ia dinilai oleh dunia.
Menilai Kesesuaian Scope & Etika Proses
Memilih jurnal tidak cukup hanya menghindari predator; kita juga harus memastikan kesesuaian antara naskah dan scope jurnal. Scope meliputi bidang, topik, metodologi, dan target pembaca. Menyerahkan naskah yang tidak sesuai scope akan membuang waktu penulis maupun editor, dan bisa menurunkan reputasi. Selain itu, menilai etika proses juga penting: apakah jurnal transparan dalam peer review, jelas dalam menyampaikan biaya publikasi (APC), dan terbuka mengenai kebijakan data dan open access. Jurnal bereputasi biasanya mencantumkan pedoman penulis (author guidelines) secara rinci, termasuk kebijakan etika, hak cipta, dan pedoman pelaporan. Indikator lain adalah keterlibatan jurnal dengan organisasi etika publikasi seperti COPE, DOAJ, OASPA, atau WAME. Jangan hanya mengejar impact factor—lebih baik artikel Anda dipublikasikan di jurnal yang pembacanya relevan dan prosesnya etis. Singkatnya, pilihlah jurnal yang bukan hanya bergengsi, tetapi juga “ramah etika”: jelas, transparan, dan selaras dengan tujuan penelitian Anda.
AI/LLM dalam Penulisan Ilmiah
Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dan Large Language Models (LLM) dalam penulisan ilmiah kini menjadi perdebatan hangat. Alat seperti ChatGPT, Grammarly, atau software otomatisasi gambar dapat membantu mempercepat penulisan, menyusun draf, atau memperbaiki tata bahasa. Namun, ada garis batas etis yang tidak boleh dilewati. AI bukan entitas yang mampu bertanggung jawab atas isi ilmiah; ia hanya alat bantu. Oleh karena itu, penggunaannya harus transparan dan diungkapkan. Banyak penerbit besar kini mewajibkan pernyataan penggunaan AI dalam acknowledgments atau bagian metode. AI juga tidak boleh digunakan untuk menghasilkan data, analisis, atau interpretasi tanpa verifikasi manusia. Penggunaan yang tidak diungkap bisa dianggap manipulatif, dan berisiko melanggar etika publikasi. Prinsipnya sederhana: AI adalah asisten, bukan penulis. Manusia tetap bertanggung jawab penuh atas keaslian, akurasi, dan integritas naskah.
Kebijakan ICMJE: AI Bukan Penulis, Wajib Diungkap
Menurut pembaruan terbaru ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors), AI tidak dapat dicantumkan sebagai penulis. Alasannya jelas: AI tidak bisa memenuhi empat kriteria kepengarangan ICMJE, terutama soal akuntabilitas penuh atas isi artikel. Jika AI digunakan—misalnya untuk menyusun draft teks, memperbaiki bahasa, menganalisis referensi, atau membuat gambar—maka penggunaannya harus diungkap secara jelas. Biasanya, penulis diwajibkan menambahkan catatan di acknowledgments atau bagian metode, misalnya: “Penulis menggunakan ChatGPT untuk membantu penyusunan draf awal dan telah memverifikasi seluruh konten.” Dengan demikian, transparansi tetap terjaga. Editor dan reviewer berhak tahu sejauh mana AI terlibat, agar bisa menilai potensi bias atau kesalahan. Etika di sini bukan soal melarang total, tetapi memastikan bahwa AI diperlakukan sebagai alat bantu teknis, bukan kontributor intelektual.
Penggunaan yang Etis: Batas, Audit Trail, dan Atribusi
Penggunaan AI yang etis mensyaratkan tiga hal: batas, audit trail, dan atribusi. Pertama, batas: AI sebaiknya hanya digunakan untuk tugas teknis (penyuntingan bahasa, format referensi) atau pendukung (membuat ilustrasi sederhana), bukan untuk menghasilkan data, hasil, atau kesimpulan. Kedua, audit trail: simpan catatan bagaimana dan kapan AI digunakan, serta apa hasilnya. Ini akan memudahkan jika editor menanyakan detail. Ketiga, atribusi: selalu cantumkan pengakuan penggunaan AI. Jika AI digunakan untuk analisis statistik, pastikan hasil diverifikasi manual oleh penulis. Jangan biarkan AI menjadi “kotak hitam” yang tidak bisa dijelaskan. Intinya, perlakukan AI seperti software lain—bisa membantu, tetapi tanggung jawab tetap ada pada penulis. Dengan sikap etis ini, AI bisa memperkaya proses penulisan tanpa merusak kredibilitas ilmiah.
Etika Sitasi: Akurat, Relevan, dan Bebas Manipulasi
Sitasi adalah bagian penting dari penulisan ilmiah: ia menghubungkan karya Anda dengan literatur sebelumnya, menunjukkan landasan teori, dan memberikan kredit pada penulis lain. Namun, sitasi juga bisa disalahgunakan. Etika sitasi menuntut bahwa rujukan harus akurat, relevan, dan jujur. Jangan mengutip artikel hanya karena populer atau berasal dari jurnal bergengsi jika tidak relevan. Jangan pula melakukan overcitation (mengutip berlebihan demi “menyemarakkan” daftar pustaka). Lebih berbahaya lagi, ada praktik manipulatif seperti citation stacking (sekelompok jurnal saling menyitir secara berlebihan untuk menaikkan impact factor) dan coercive citation (editor atau reviewer meminta penulis menambahkan sitasi ke artikel jurnal tertentu tanpa alasan ilmiah yang sah). Praktik ini jelas melanggar etika publikasi karena merusak ekosistem sitasi. Sitasi yang baik harus transparan: kutip sumber asli, bukan sekadar review atau kutipan kedua. Jika Anda mengutip pernyataan, pastikan sesuai konteks dan jangan mengubah makna. Singkatnya, sitasi etis adalah soal menghormati karya orang lain tanpa manipulasi untuk kepentingan pribadi atau institusi.
Citation Stacking, Coercive Citation & Cara Menghindari
Citation stacking biasanya dilakukan antarjurnal atau antarpenulis yang sepakat saling menyitir secara berlebihan untuk meningkatkan impact. Coercive citation, di sisi lain, muncul saat editor/reviewer meminta penulis menambahkan sitasi ke artikel tertentu agar meningkatkan reputasi jurnal. Kedua praktik ini dianggap manipulasi ilmiah dan dapat memicu sanksi dari penerbit maupun lembaga pengindeks. Cara menghindarinya: (1) fokus pada kualitas, bukan kuantitas sitasi, (2) prioritaskan sumber primer dan studi yang benar-benar relevan, (3) jika reviewer meminta tambahan sitasi, evaluasi apakah benar-benar relevan; jika tidak, jelaskan alasan penolakan secara sopan, (4) gunakan perangkat manajemen referensi agar sitasi konsisten dan akurat. Banyak jurnal kini bekerja sama dengan COPE untuk mendeteksi pola sitasi abnormal. Ingat, sitasi bukan sekadar formalitas; ia adalah jejak intelektual yang menunjukkan integritas penulis dalam menempatkan karya di peta pengetahuan.
Koreksi, Erratum, Corrigendum, dan Addendum
Tidak ada penelitian yang sempurna; kesalahan bisa muncul dalam bentuk salah ketik, data yang terlewat, atau bahkan interpretasi yang kurang tepat. Untuk itulah ada mekanisme erratum, corrigendum, dan addendum. Erratum biasanya dikeluarkan oleh penerbit untuk memperbaiki kesalahan teknis (misalnya salah cetak tabel atau grafik). Corrigendum dikeluarkan oleh penulis untuk memperbaiki kesalahan yang berasal dari mereka, seperti data salah input atau analisis yang keliru. Addendum ditambahkan ketika ada informasi penting yang relevan dengan artikel tetapi muncul setelah publikasi. Semua ini adalah bagian dari etika penulisan ilmiah: mengakui bahwa kesalahan adalah bagian dari proses sains, dan memperbaikinya adalah tanggung jawab profesional. Yang perlu dihindari adalah menyembunyikan atau mengabaikan kesalahan, karena itu justru bisa merusak reputasi dan kredibilitas.
Mengakui Kekeliruan secara Bertanggung Jawab
Mengakui kekeliruan bukan tanda kelemahan, tetapi bukti integritas. Banyak ilmuwan besar dalam sejarah yang justru dihormati karena keberanian mereka menarik atau memperbaiki karya mereka. Proses koreksi bukan hanya menyelamatkan reputasi penulis, tetapi juga melindungi literatur agar tidak bias. Penulis sebaiknya segera menghubungi editor ketika menemukan kesalahan substansial pada artikelnya. Jika perlu retraction, lakukan secara transparan dan sertakan alasan jelas. COPE menyarankan bahwa retraction harus tetap tersedia secara publik, bukan dihapus, agar pembaca tahu alasan penarikan dan tidak mengutipnya lagi. Dalam beberapa kasus, koreksi justru meningkatkan sitasi karena menunjukkan komitmen pada integritas. Jadi, jangan takut memperbaiki kesalahan; yang lebih berbahaya adalah membiarkannya beredar tanpa klarifikasi.
Publikasi Ganda Lintas Bahasa & Terjemahan
Publikasi ganda atau duplicate publication adalah salah satu bentuk pelanggaran etika yang paling sering diperdebatkan. Salah satunya adalah kasus artikel yang dipublikasikan ulang dalam bahasa berbeda, misalnya versi bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris. Apakah ini boleh? Jawabannya: boleh dengan syarat transparansi penuh. Penulis wajib mengungkapkan bahwa artikel tersebut sudah pernah diterbitkan dalam bahasa lain, menyebutkan sumber publikasi pertama, serta mendapatkan izin dari penerbit sebelumnya. Jika tidak, praktik ini bisa dianggap sebagai redundant publication yang memperburuk integritas literatur ilmiah. Jurnal bereputasi biasanya memiliki kebijakan khusus soal ini. Misalnya, artikel yang diterjemahkan harus menyertakan catatan kaki atau pernyataan editor bahwa itu adalah versi lain dari publikasi sebelumnya. Intinya, publikasi lintas bahasa diperbolehkan, tetapi harus jujur, terbuka, dan tidak menyesatkan pembaca.
Kapan Diperbolehkan dan Syarat Transparansinya
Publikasi ganda lintas bahasa dapat diperbolehkan dalam konteks tertentu, misalnya untuk memperluas akses pembaca di negara berbeda. Namun, ada beberapa syarat utama:
- Izin penerbit – Artikel pertama kali diterbitkan harus memberikan izin tertulis untuk publikasi ulang dalam bahasa lain.
- Transparansi – Penulis wajib mencantumkan catatan bahwa artikel tersebut adalah terjemahan dari publikasi sebelumnya.
- Sumber jelas – Referensi artikel asli harus tercantum di awal atau akhir tulisan.
- Tidak ada perubahan substansial – Jika ada tambahan data atau analisis, sebaiknya artikel tersebut dianggap sebagai “versi diperluas”, bukan sekadar terjemahan.
Dengan mengikuti aturan ini, publikasi lintas bahasa bisa menjadi cara efektif untuk menjembatani kesenjangan literasi ilmiah tanpa melanggar etika.
Kolaborasi Internasional & Multi-Disiplin
Penelitian masa kini semakin sering dilakukan dalam kolaborasi lintas negara dan lintas disiplin. Kolaborasi internasional memberi peluang besar: akses sumber daya global, variasi metode, serta dampak publikasi yang lebih luas. Namun, di balik itu ada tantangan etis yang perlu dikelola. Perbedaan budaya riset, regulasi negara, hingga ekspektasi penulis dapat menimbulkan konflik jika tidak ada kesepakatan sejak awal. Etika kolaborasi menekankan kejelasan peran, kepemilikan data, dan pembagian kredit publikasi. Penting juga untuk memastikan semua pihak mematuhi standar internasional, misalnya tentang uji etik penelitian manusia/hewan, akses data, serta kepengarangan. Kolaborasi yang etis bukan hanya menghasilkan artikel berkualitas tinggi, tetapi juga memperkuat jaringan akademik yang sehat.
Perjanjian Peran Sejak Proposal
Untuk mencegah konflik, disarankan agar semua kolaborator membuat written agreement sejak tahap proposal. Perjanjian ini biasanya mencakup:
- Peran tiap anggota (penanggung jawab data, analisis, penulisan, dll.)
- Kepemilikan data dan aturan berbagi data (data sharing policy).
- Urutan kepengarangan (authorship order).
- Rencana publikasi termasuk target jurnal dan kebijakan open access.
Dokumen ini bisa berupa Memorandum of Understanding (MoU) atau Data Sharing Agreement. Dengan cara ini, semua anggota memiliki acuan etis yang jelas, dan potensi perselisihan di tahap akhir bisa dihindari.
Peran Editor, Penerbit, & Institusi
Etika penulisan ilmiah tidak hanya tanggung jawab penulis, tetapi juga melibatkan editor, penerbit, dan institusi akademik. Editor bertugas menjaga integritas publikasi dengan memastikan proses peer review adil, transparan, dan bebas konflik kepentingan. Penerbit wajib menyediakan kebijakan etika yang jelas, melindungi hak cipta, dan tidak terlibat dalam praktik predator. Institusi pendidikan atau riset juga berperan besar: mereka harus membina mahasiswa dan dosen tentang etika publikasi, menyediakan pelatihan, dan menegakkan sanksi bila ada pelanggaran. Etika publikasi adalah ekosistem: jika salah satu pihak abai, keseluruhan sistem bisa rusak. Oleh karena itu, kerja sama antar pemangku kepentingan menjadi kunci menjaga kualitas literatur ilmiah global.
COPE & Kode Etik untuk Seluruh Pemangku Kepentingan
Banyak jurnal internasional kini mengacu pada pedoman COPE (Committee on Publication Ethics) yang memberi panduan tentang plagiarisme, duplikasi, konflik kepentingan, dan retraction. Selain COPE, ada juga ICMJE, WAME, OASPA, dan CSE yang masing-masing memiliki standar etika khusus. Dengan mengadopsi pedoman ini, editor dan penerbit memiliki landasan kuat untuk menangani kasus pelanggaran etika. Institusi pun diharapkan mengintegrasikan pedoman ini ke dalam SOP penelitian. Jadi, bukan hanya penulis yang dituntut menjaga integritas, tetapi seluruh ekosistem publikasi ilmiah.
Tabel Ringkas: Checklist Etika Penulisan Ilmiah
Untuk memudahkan praktisi, berikut adalah tabel ringkas sebagai panduan:
| Tahap | Checklist Etika |
| Sebelum Submisi | Pastikan keaslian, hindari plagiarisme, tentukan penulis dengan adil, siapkan izin etik (jika ada manusia/hewan), cek relevansi jurnal. |
| Saat Submisi | Ungkap penggunaan AI (jika ada), sertakan konflik kepentingan, pastikan data akurat, ikuti author guidelines. |
| Setelah Submisi | Respon reviewer dengan sopan, perbaiki kesalahan bila ditemukan, transparan soal erratum/corrigendum, hindari duplikasi publikasi. |
Checklist ini bisa menjadi alat sederhana untuk memastikan setiap tahap publikasi tetap dalam jalur etis.
Studi Kasus Singkat
Bayangkan seorang peneliti yang memutuskan menerjemahkan artikelnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris tanpa izin penerbit pertama. Artikel itu kemudian ditemukan oleh editor jurnal internasional, yang lalu menuduh penulis melakukan duplicate publication. Reputasi penulis pun dipertaruhkan, dan akhirnya artikel ditarik. Dari kasus ini kita belajar bahwa transparansi adalah kunci. Studi kasus lain: sebuah tim riset internasional gagal menyepakati urutan kepengarangan sejak awal. Ketika artikel diterima, terjadi konflik serius yang berujung pada keterlambatan publikasi. Pelajaran utamanya: buat perjanjian peran sejak awal untuk menghindari sengketa.
Analisis dan Pelajaran yang Bisa Diambil
Dari dua studi kasus di atas, jelas bahwa pelanggaran etika sering kali bukan karena niat buruk, tetapi karena kurangnya pemahaman atau pengaturan sejak awal. Maka, edukasi dan kesepakatan tertulis menjadi solusi utama. Etika publikasi bukan sekadar aturan formal, tetapi jembatan untuk menjaga kepercayaan di komunitas ilmiah.
Langkah Implementasi di Kampus/Tim Riset
Bagaimana cara membawa etika penulisan ilmiah ke level praktis? Jawabannya: melalui SOP, pelatihan, dan monitoring. Kampus atau institusi riset sebaiknya membuat standar prosedur publikasi yang merujuk ke COPE/ICMJE. Mahasiswa dan peneliti harus rutin mengikuti pelatihan etika publikasi, termasuk penggunaan software pendeteksi plagiarisme dan manajemen referensi. Selain itu, perlu ada mekanisme monitoring, misalnya audit publikasi tahunan, agar kepatuhan tetap terjaga. Dengan sistem ini, etika publikasi tidak hanya menjadi teori, tetapi praktik nyata di setiap level riset.
SOP, Pelatihan, dan Monitoring
- SOP: Dokumen resmi yang memandu setiap tahap publikasi, dari proposal hingga publikasi.
- Pelatihan: Workshop rutin tentang plagiarisme, sitasi, kepengarangan, penggunaan AI, dll.
- Monitoring: Evaluasi berkala publikasi untuk mendeteksi potensi pelanggaran.
Dengan tiga langkah ini, institusi bisa menciptakan budaya riset yang sehat dan berintegritas.
Kesimpulan
Etika penulisan ilmiah adalah fondasi yang menjaga sains tetap dipercaya. Ia meliputi integritas data, kepengarangan yang adil, transparansi penggunaan AI, sitasi yang akurat, serta tanggung jawab dalam mengoreksi kesalahan. Etika bukan hanya urusan penulis, tetapi seluruh ekosistem: editor, penerbit, dan institusi. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, peneliti bisa menghasilkan karya yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga berkontribusi positif bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Pada akhirnya, publikasi ilmiah bukan hanya soal “publish or perish”, melainkan “publish with integrity”.
Referensi
- COPE. 2025. Authorship and AI Tools. Committee on Publication Ethics. https://publicationethics.org/guidance/cope-position/authorship-and-ai-tools.
- COPE. 2025. Retraction Guidelines. Committee on Publication Ethics. https://publicationethics.org/guidance/guideline/retraction-guidelines.
- Elsevier. 2025. Publishing Ethics Policy. Elsevier. https://www.elsevier.com/about/policies-and-standards/publishing-ethics.
- Elsevier. 2025. Scopus Content Policy and Selection. Elsevier. https://www.elsevier.com/products/scopus/content/content-policy-and-selection.
- Ganjavi, Conner, A. J. London, A. McCoy, dan J. F. Dever. 2023. “Bibliometric Analysis of Publisher and Journal Instructions to Authors on Generative-AI.” arXiv preprint arXiv:2307.11918. https://arxiv.org/abs/2307.11918.
- ICMJE. 2025. Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals. International Committee of Medical Journal Editors. https://www.icmje.org/recommendations/.
- Wager, Elizabeth. 2012. “The Committee on Publication Ethics (COPE): Objectives and Achievements 1997–2012.” La Presse Médicale 41 (9 Pt 1): 861–66. https://doi.org/10.1016/j.lpm.2012.02.016.
- Human-Machine Collaboration (HMC). 2023. Publication Ethics Statement. University of Central Florida. https://stars.library.ucf.edu/hmc/publication_ethics.html.