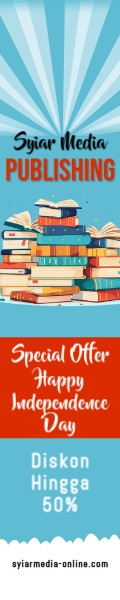Istilah gender sering disalahpahami sebagai sinonim dari “perempuan” atau “jenis kelamin”, padahal ia merujuk pada konsep yang jauh lebih kompleks dan dinamis. Berbeda dengan seks—yang merujuk pada klasifikasi biologis (laki-laki, perempuan, interseks)—gender adalah konstruksi sosial, budaya, dan psikologis tentang apa artinya menjadi “laki-laki” atau “perempuan”, serta peran, perilaku, ekspresi, dan identitas yang dikaitkan dengan keduanya. Konsep ini tidak bersifat alamiah atau tetap, melainkan dibentuk oleh masyarakat, sejarah, dan kekuasaan. Esai ini mengupas pengertian gender secara komprehensif, menelusuri evolusi konsepnya dari abad ke-20 hingga konteks global hari ini, serta mengkaji implikasinya dalam bidang pendidikan, pekerjaan, politik, dan kesehatan. Selain itu, esai ini juga menyentuh isu identitas gender non-biner dan transgender, serta mengevaluasi tantangan dan kemajuan dalam perjuangan kesetaraan gender. Dengan pendekatan interdisipliner—sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan studi budaya—esai ini bertujuan memperdalam pemahaman bahwa gender bukan takdir, melainkan pengalaman yang bisa direformasi menuju keadilan dan inklusi.
Istilah gender dalam konteks sosial pertama kali digunakan secara akademik oleh psikolog John Money pada 1955, ketika ia membedakan antara sex (biologi) dan gender identity (identitas psikologis). Namun, konsep ini menjadi populer luas melalui karya feminis Simone de Beauvoir dalam bukunya The Second Sex (1949), di mana ia menyatakan: “Wanita tidak dilahirkan, melainkan dijadikan.” Pernyataan ini menjadi fondasi penting: menjadi perempuan atau laki-laki bukan hasil biologi semata, tetapi proses sosialisasi. Pada 1970-an, feminis seperti Judith Butler, Gayle Rubin, dan Sandra Harding memperluas konsep ini dengan memperkenalkan ide bahwa gender adalah performa (gender performativity), yaitu tindakan berulang yang menciptakan ilusi “alami” tentang gender. Dalam perkembangannya, konsep gender melampaui dikotomi laki-laki-perempuan, membuka ruang bagi identitas seperti non-biner, genderqueer, dan agender. Hari ini, gender dipahami bukan sebagai kategori tetap, tetapi sebagai spektrum dinamis yang dipengaruhi oleh budaya, sejarah, dan relasi kuasa.
Gender tidak ditentukan oleh biologi, tetapi dibentuk oleh masyarakat melalui norma, institusi, dan praktik sehari-hari. Sejak lahir, anak-anak dikategorikan sebagai “laki-laki” atau “perempuan” berdasarkan organ genital, lalu diberi warna (biru/merah muda), mainan (mobil/boneka), dan harapan perilaku (“jangan menangis, kamu laki-laki!”). Proses ini disebut sosialisasi gender, yang terjadi melalui keluarga, sekolah, media, dan agama. Sosiolog seperti Candace West dan Don Zimmerman menyebutnya sebagai “doing gender”—tindakan sehari-hari yang terus-menerus memproduksi identitas gender. Misalnya, cara berjalan, berbicara, bahkan mengatur ekspresi wajah, semuanya diatur oleh norma gender. Konstruksi ini bersifat hierarkis: masyarakat cenderung memposisikan laki-laki sebagai dominan dan perempuan sebagai subordinat. Struktur ini memperkuat patriarki, yaitu sistem sosial yang memberi kekuasaan lebih kepada laki-laki. Dalam konteks global, konstruksi gender bervariasi: di beberapa masyarakat adat, seperti suku Bugis di Sulawesi atau Two-Spirit dalam budaya Native American, dikenal lebih dari dua gender. Ini membuktikan bahwa gender adalah produk budaya, bukan hukum alam.
Gender memengaruhi hampir semua aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam dunia kerja, perempuan sering menghadapi segregasi horizontal dan vertikal: mereka terkonsentrasi di sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi (horizontal), dan jarang mencapai posisi kepemimpinan (vertikal). Fenomena ini dikenal sebagai glass ceiling (langit-langit kaca). Menurut ILO (2023), perempuan hanya menduduki 28% posisi manajerial global. Di Indonesia, BPS (2024) mencatat kesenjangan upah gender sebesar 30%. Dalam rumah tangga, perempuan masih menjadi penanggung jawab utama pekerjaan domestik dan pengasuhan anak, meskipun bekerja di luar rumah—fenomena yang disebut “double burden” atau “second shift”. Dalam politik, representasi perempuan masih rendah: hanya 26% anggota parlemen dunia yang perempuan (IPU, 2023), dan di Indonesia sekitar 21%. Selain itu, kekerasan berbasis gender (seperti KDRT, pelecehan seksual, dan femicide) tetap menjadi ancaman serius. Semua ini menunjukkan bahwa struktur sosial tidak netral, tetapi dibentuk oleh asumsi gender yang diskriminatif, yang harus diubah melalui kebijakan, pendidikan, dan kesadaran kolektif.
Meskipun masyarakat umumnya mengenal hanya dua gender, kenyataannya identitas gender jauh lebih beragam. Banyak orang tidak merasa cocok dengan kategori laki-laki atau perempuan, dan mengidentifikasi diri sebagai non-biner, genderfluid, agender, atau transgender. Transgender adalah mereka yang identitas gendernya tidak sesuai dengan seks biologis saat lahir. Non-biner merujuk pada identitas yang berada di luar spektrum laki-laki-perempuan. Komunitas ini telah lama ada, tetapi baru mendapat pengakuan akademik dan hukum dalam beberapa dekade terakhir. Negara-negara seperti Kanada, Australia, dan India telah mengakui identitas gender non-biner dalam dokumen resmi. Di Indonesia, meskipun belum ada pengakuan hukum, komunitas seperti waria (wanita-pria) telah eksis selama berabad-abad, terutama dalam budaya Bugis dan Minangkabau. WHO (2019) telah menghapus “gangguan identitas gender” dari daftar penyakit mental, mengakui bahwa transgender bukan kelainan, melainkan variasi manusia. Menghormati keberagaman gender bukan soal “ikut tren Barat”, tetapi soal hak asasi manusia, kesehatan mental, dan keadilan sosial.
Perjuangan kesetaraan gender telah melalui beberapa gelombang. Feminisme gelombang pertama (akhir abad ke-19–awal 20) memperjuangkan hak pilih dan pendidikan perempuan. Gelombang kedua (1960–1980-an) menyerang struktur patriarki, menuntut kesetaraan di tempat kerja, dan mengeksplorasi isu seksualitas dan tubuh perempuan. Gelombang ketiga (1990-an–2000-an) menekankan keragaman perempuan—perempuan kulit hitam, lesbian, miskin—dan mengkritik feminisme Barat yang homogen. Gelombang keempat (2010–sekarang) difasilitasi media sosial, dengan kampanye seperti #MeToo, #TimesUp, dan #NiUnaMenos yang menyerukan akuntabilitas terhadap kekerasan seksual. Di dunia Muslim, muncul feminisme Islam yang mengkaji ulang teks-teks agama dari sudut pandang perempuan, dengan tokoh seperti Amina Wadud, Nurkolis Madjid, dan Siti Musdah Mulia. Mereka menunjukkan bahwa Islam tidak menjustifikasi diskriminasi, tetapi sering ditafsirkan secara patriarkal. Gerakan ini menunjukkan bahwa perjuangan gender bukan hanya Barat, tetapi global, inklusif, dan terus berkembang.
Meskipun telah banyak kemajuan, tantangan kesetaraan gender masih besar. Stigma terhadap perempuan karier, orang transgender, atau laki-laki yang menolak norma maskulinitas toksik masih kuat. Di banyak negara, termasuk Indonesia, RUU yang mendukung kesetaraan seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menghadapi penolakan dari kelompok konservatif. Selain itu, media dan budaya populer sering memperkuat stereotip gender, misalnya dengan mempromosikan tubuh “ideal” atau peran tradisional. Namun, ada harapan: generasi muda, terutama Gen Z, menunjukkan tingkat penerimaan yang lebih tinggi terhadap keberagaman gender. Pendidikan gender kini mulai masuk kurikulum sekolah di beberapa negara. Perusahaan global menerapkan kebijakan gender-neutral, dan media mulai menampilkan tokoh non-biner. Untuk masa depan, dibutuhkan pendekatan holistik: hukum yang adil, pendidikan yang inklusif, media yang bertanggung jawab, dan kesadaran bahwa kesetaraan gender menguntungkan semua pihak, termasuk laki-laki yang juga terbelenggu oleh norma maskulinitas.
Gender bukanlah takdir biologis, melainkan produk sosial yang bisa diubah. Memahami gender berarti mengakui bahwa peran, identitas, dan harapan terhadap laki-laki dan perempuan bukan alamiah, tetapi dibentuk oleh kekuasaan, budaya, dan sejarah. Perjuangan kesetaraan gender bukan tentang mengganti dominasi laki-laki dengan dominasi perempuan, tetapi tentang menghancurkan sistem hierarki yang merugikan semua pihak. Laki-laki juga dirugikan oleh norma maskulinitas yang menuntut mereka untuk tidak menangis, tidak peduli, dan selalu kuat. Masyarakat yang adil adalah yang menghormati pilihan, identitas, dan martabat setiap individu, tanpa memandang gender. Dari pengakuan hak transgender hingga penghapusan kesenjangan upah, dari pendidikan inklusif hingga reformasi tafsir agama—langkah-langkah ini adalah bagian dari peradaban yang lebih manusiawi. Seperti yang dikatakan bell hooks: “Feminisme adalah gerakan untuk mengakhiri dominasi, baik terhadap perempuan, anak-anak, maupun laki-laki.” Di situlah letak masa depan yang kita tuju.
Rujukan
- Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity.
- de Beauvoir, S. (1949). The Second Sex.
- World Health Organization (WHO). (2023). Gender and Health.
- International Labour Organization (ILO). (2023). Global Wage Report.
- Inter-Parliamentary Union (IPU). (2023). Women in National Parliaments.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Statistik Gender dan Ketenagakerjaan di Indonesia.
- Wadud, A. (1999). Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective.
- Rubin, G. (1975). The Traffic in Women: Notes on the Political Economy of Sex.
- United Nations. (2020). Progress on the Sustainable Development Goals: Gender Equality.
- Azra, Azyumardi. (2006). Islam Substantif dan Islam Formalistik.