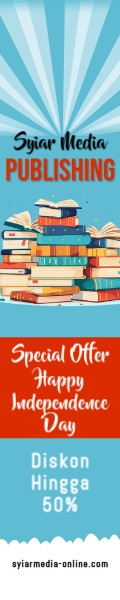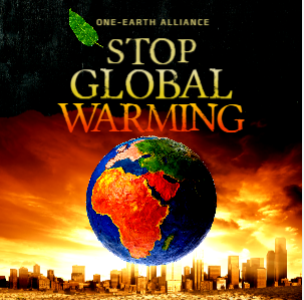Dalam dua dekade terakhir, dunia menyaksikan peningkatan drastis dalam frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem: banjir besar, kekeringan panjang, gelombang panas, dan kebakaran hutan. Menurut laporan IPCC (2023), suhu rata-rata global telah naik 1,2°C sejak era pra-industri, dan umat manusia berada di ambang krisis iklim yang mengancam keberlangsungan kehidupan. Fenomena ini bukan sekadar isu sains atau kebijakan, tetapi juga ujian moral dan spiritual. Dalam konteks Islam, Al-Qur’an menawarkan pandangan holistik tentang hubungan manusia dengan alam, menempatkan manusia sebagai khalifah fil ardh (wakil Tuhan di bumi), yang diberi amanah untuk memelihara, bukan merusak. Esai ini mengkaji krisis iklim dan cuaca ekstrem dari lensa Al-Qur’an dan tafsir klasik-modern, menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya pelanggaran terhadap ekosistem, tetapi pelanggaran terhadap janji kepada Allah. Dengan mengintegrasikan wawasan ilmiah dan keagamaan, esai ini menyerukan pemulihan kesadaran teologis sebagai dasar gerakan ekologis dalam dunia Muslim.
Al-Qur’an tidak memandang alam sebagai objek mati yang bisa dieksploitasi semaunya, melainkan sebagai tanda-tanda (ayat) kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Firman-Nya:
“Dan pada penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, serta kapal-kapal yang berlayar di laut membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering), dan Dia sebarkan di bumi segala jenis hewan, dan pengaturan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berakal.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 164)
Ayat ini menekankan bahwa alam adalah ayat yang harus dibaca dengan akal dan hati, bukan dieksploitasi tanpa refleksi. Konsep mīzān (keseimbangan) menjadi poros kosmologi Qur’ani:
“Dan langit telah Kami bangun dengan kekuasaan, dan sesungguhnya Kami adalah Maha Luas. Dan Kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran (qadar).”
(QS. Al-Dzariyat [51]: 47–49)
Keseimbangan ini kini terganggu oleh aktivitas manusia—emisi karbon, deforestasi, polusi—yang menyebabkan gangguan iklim sistemik. Tafsir modern seperti karya Fazlun Khalid dalam Islam and Ecology menegaskan bahwa merusak mīzān berarti menentang sunnatullah (hukum alam yang ditetapkan Allah), dan akan berujung pada fasād fil ardh (kerusakan di bumi).
Salah satu istilah paling sentral dalam diskusi ekologi Qur’ani adalah fasād fil ardh (kerusakan di muka bumi), yang disebutkan berulang kali dalam Al-Qur’an:
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya…”
(QS. Al-A’raf [7]: 56)
Kata fasād tidak hanya berarti kekacauan sosial, tetapi juga kerusakan ekologis, termasuk penebangan hutan, pencemaran air, dan kepunahan spesies. Dalam tafsir Ibn Kathir, fasād dikaitkan dengan tindakan manusia yang melampaui batas (ta’addi al-hudud), baik secara moral maupun ekologis. Allah berfirman:
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”
(QS. Ar-Rum [30]: 41)
Ayat ini sangat relevan: krisis iklim adalah konsekuensi langsung dari eksploitasi berlebihan oleh manusia. Cuaca ekstrem—banjir, kekeringan, topan—bukan bencana alam murni, tetapi peringatan (‘ibrah) dari Allah agar manusia bertobat dan kembali menjalankan amanah sebagai khalifah. Jika tidak, kerusakan akan terus berlipat, sebagaimana dinyatakan dalam ayat-ayat lain tentang azab yang diturunkan karena kezaliman manusia terhadap bumi.
Allah berfirman:
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.'”
(QS. Al-Baqarah [2]: 30)
Kata khalifah (wakil, pengganti) menunjukkan bahwa manusia bukan pemilik bumi, melainkan penjaga sementara yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam tafsir al-Razi, khalifah bukan berarti dominasi, tetapi tanggung jawab (taklif) untuk memelihara kehidupan, keadilan, dan keseimbangan. Konsep ini bertentangan dengan pandangan antroposentris yang melihat alam sebagai sumber daya tak terbatas. Di era kapitalisme ekologis, banyak manusia telah mengganti peran khalifah dengan mustakmir (penjajah bumi), merusak hutan demi sawit, laut demi sampah plastik, dan udara demi emisi karbon. Ulama kontemporer seperti Syed Hossein Nasr menegaskan bahwa krisis iklim adalah krisis spiritual: manusia telah lupa bahwa bumi bukan miliknya, melainkan amanah ilahi. Maka, solusi bukan hanya teknologi, tetapi pemulihan kesadaran teologis—kembali kepada prinsip khalifah rahmah, yaitu kepemimpinan yang penuh kasih sayang terhadap seluruh makhluk.
Tafsir klasik sering kali fokus pada aspek hukum dan teologis, tetapi tafsir kontemporer mulai mengintegrasikan ilmu pengetahuan. Ulama seperti Nurcholish Madjid dan Fazlun Khalid menawarkan tafsir ekologis yang membaca ayat-ayat tentang alam sebagai dorongan untuk menjaga lingkungan. Misalnya, QS. Al-A’raf [7]: 31:
“Dan janganlah kamu boros (israf); sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang boros.”
Dalam konteks modern, israf tidak hanya berlaku pada makanan, tetapi juga pada konsumsi energi, air, dan sumber daya alam. Seorang Muslim yang menggunakan mobil besar untuk perjalanan dekat, membuang makanan, atau menyalakan AC sepanjang hari, bisa dikatakan berbuat israf—dosa yang disebutkan langsung dalam Al-Qur’an. Demikian pula, QS. Al-An’am [6]: 141:
“Dan Dia menumbuhkan kebun-kebun yang dipanjat, dan kebun kurma, dan tanaman-tanaman yang beraneka buahnya, dan zaitun, dan granat…”
Ayat ini menunjukkan keberagaman hayati sebagai nikmat. Merusak biodiversitas berarti mengingkari nikmat tersebut. Tafsir modern menyerukan agar umat Islam melihat laboratorium iklim, laporan IPCC, dan data suhu global sebagai bentuk “ayat” baru yang harus dibaca sebagaimana membaca Al-Qur’an—dengan rasa takut, tanggung jawab, dan keinginan untuk berubah.
Beberapa inisiatif global telah muncul untuk menghidupkan kembali etika ekologis Islam. Di Indonesia, MUI telah mengeluarkan Fatwa Lingkungan Hidup (2010) yang mengharamkan perusakan hutan dan mewajibkan penghijauan. Organisasi seperti Green Mosque Initiative dan Jaringan Muslim untuk Iklim mendorong masjid-masjid menjadi pusat edukasi lingkungan. Di Maroko, masjid-masjid mulai menggunakan panel surya. Di UEA, diluncurkan Qur’an and Climate Change Campaign. Bahkan, Hijau Qur’an—edisi Al-Qur’an yang dicetak dengan tinta ramah lingkungan dan kertas daur ulang—telah diperkenalkan. Ini adalah wujud dari tafsir hidup: membaca Al-Qur’an tidak hanya dengan lidah, tetapi dengan tindakan. Umat Islam, dengan lebih dari 1,8 miliar jiwa dan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim (seperti pesisir, gurun, dan pulau kecil), memiliki tanggung jawab kolektif untuk menjadi pelopor dalam gerakan iklim. Dari pengurangan plastik sekali pakai hingga kampanye urban farming di kompleks masjid, setiap aksi kecil adalah bentuk ibadah ekologis.
Krisis iklim dan cuaca ekstrem bukan hanya tantangan ilmiah, tetapi ujian iman. Al-Qur’an telah jelas menyatakan bahwa manusia adalah khalifah, diberi akal, dan diperingatkan terhadap fasād fil ardh. Ketika banjir melanda Jakarta, kekeringan menghantam Nusa Tenggara, atau suhu menyentuh 40°C di kota-kota besar, kita harus bertanya: apakah kita masih menjalankan amanah ini? Tafsir Al-Qur’an tidak boleh terkurung dalam kitab klasik, tetapi harus hidup dalam kebijakan, gaya hidup, dan gerakan sosial. Seperti yang dikatakan Fazlun Khalid, “Muslim tidak perlu menjadi ahli lingkungan untuk menyelamatkan bumi; cukup menjadi Muslim yang benar-benar membaca Al-Qur’an.” Maka, solusi terhadap krisis iklim bukan hanya teknologi atau regulasi, tetapi pemulihan hubungan spiritual manusia dengan pencipta dan ciptaan-Nya. Di akhirat, bukan hanya ibadah ritual yang akan ditanya, tetapi juga: “Apa yang kamu lakukan dengan bumi-Ku?”
Rujukan
- Al-Qur’an, terjemahan dan tafsir Departemen Agama RI.
- Ibn Kathir. Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim.
- Fazlun Khalid. (2002). Islam and Ecology: A Best Practice Model for Sustainability.
- Nasr, S. H. (1968). Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man.
- IPCC. (2023). Sixth Assessment Report (AR6).
- MUI. (2010). Fatwa tentang Lingkungan Hidup.
- Khalid, F., & O’Brien, J. (Eds.). (1992). Islam and Ecology. Harvard University Press.
- Roudhah Institute. (2023). Tafsir Ekologis Al-Qur’an.
- BMKG. (2024). Laporan Cuaca Ekstrem di Indonesia.
- United Nations. (2023). Climate Change and Faith-Based Action.