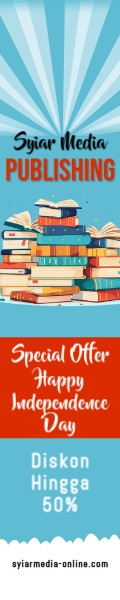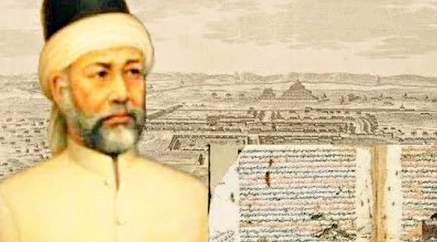Di tengah maraknya tafsir-tafsir Al-Qur’an yang berasal dari dunia Arab, Timur Tengah, atau Barat, keberadaan Tafsir Tarjuman al-Mustafid karya Abdurrauf as-Singkili (w. 1693 M) menempati posisi unik dan strategis dalam sejarah intelektual Islam Nusantara. Karya ini bukan sekadar terjemahan atau penjelasan Al-Qur’an, melainkan jembatan budaya, bahasa, dan spiritualitas yang menghubungkan dunia Islam klasik dengan realitas masyarakat Melayu abad ke-17. Ditulis dalam bahasa Melayu klasik, Tarjuman al-Mustafid menjadi salah satu tafsir paling awal dan berpengaruh dalam tradisi Islam Nusantara. Penulisnya, Abdurrauf ibn Ali al-Fansuri al-Sinkili—lebih dikenal sebagai Abdurrauf as-Singkili—adalah seorang ulama sufi yang pernah menuntut ilmu di Mekkah selama lebih dari dua puluh tahun, berguru langsung kepada tokoh-tokoh besar seperti Syekh Ahmad al-Qusyairi dan Syekh Ibrahim al-Kurani. Esai ini mengkaji secara mendalam latar belakang, metode, ciri khas, dan signifikansi Tarjuman al-Mustafid sebagai karya tafsir yang menggabungkan keilmuan syariat, tasawuf, dan kontekstualisasi lokal, serta menilai warisan intelektualnya bagi perkembangan Islam di Indonesia hingga hari ini.
Abdurrauf as-Singkili lahir di Singkil, Aceh, sekitar tahun 1615 M, dan karena itu dikenal dengan sebutan al-Sinkili. Ia menuntut ilmu di pusat-pusat keilmuan Islam, terutama di Mekkah dan Madinah, selama lebih dari dua dekade, di mana ia menguasai berbagai disiplin ilmu: tafsir, hadis, fikih, kalam, dan terutama tasawuf. Ia menjadi murid utama dari Syekh Ahmad al-Qusyairi, seorang tokoh sufi besar dari ordo Syattariyah, dan kemudian diangkat sebagai khalifah (penerus spiritual) dalam tarekat tersebut. Setelah kembali ke Aceh sekitar tahun 1665 M, ia diangkat sebagai Mufti Kerajaan Aceh oleh Sultan Iskandar Thani, dan menjadi guru spiritual bagi para bangsawan dan ulama. Karya-karyanya tidak hanya berupa tafsir, tetapi juga risalah tasawuf seperti Mir’at al-Thalibin dan al-Hikam al-Muhammadiyah. Namun, Tarjuman al-Mustafid menjadi karyanya yang paling monumental karena sifatnya yang edukatif, sistematis, dan mudah diakses oleh masyarakat awam Melayu. Ia wafat pada tahun 1693 M dan dimakamkan di Krueng Raya, Aceh Besar.
Penulisan Tarjuman al-Mustafid tidak terlepas dari konteks sosial dan keagamaan Aceh pada abad ke-17. Meskipun Islam telah berkembang kuat di Aceh, terutama di kalangan elite, pemahaman masyarakat umum terhadap Al-Qur’an masih terbatas karena ketergantungan pada bahasa Arab yang tidak dikuasai banyak orang. Selain itu, muncul kebutuhan untuk menyebarkan ajaran Islam yang seimbang antara syariat dan hakikat, mengingat tasawuf mulai berkembang pesat namun sering disalahpahami. Dalam konteks inilah Abdurrauf as-Singkili menulis Tarjuman al-Mustafid—sebagai alat edukasi massal yang menggunakan bahasa Melayu, yang saat itu menjadi lingua franca di Nusantara. Tujuannya jelas: agar umat Islam di Nusantara bisa memahami makna Al-Qur’an secara langsung, tanpa harus menguasai bahasa Arab. Ia menyebut tafsir ini sebagai “penafsir bagi yang ingin memahami” (tarjuman al-mustafid), menekankan fungsi pedagogisnya. Karya ini juga menjadi bagian dari upaya dakwah berbasis pemahaman mendalam, bukan sekadar ritual atau tradisi.
Abdurrauf as-Singkili tidak menulis tafsirnya secara improvisasi, melainkan berdasarkan rujukan-rujukan otoritatif dari dunia Islam klasik. Metodologi Tarjuman al-Mustafid tergolong sebagai tafsir bil ma’tsur (berdasarkan warisan) dan tafsir bil ra’yi (dengan ijtihad), dengan dominasi pendekatan ma’tsur. Ia banyak merujuk pada tafsir-tafsir besar seperti:
- Tafsir al-Jalalayn karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti,
- Tafsir al-Baydawi (Anwar al-Tanzil),
- Tafsir al-Khazin,
- Ruh al-Ma’ani karya al-Alusi (dalam versi yang tersedia saat itu),
- Dan karya-karya fikih serta tasawuf yang relevan.
Namun, yang membedakannya adalah kemampuannya menyederhanakan bahasa dan menyusun ulang penjelasan agar sesuai dengan logika dan budaya Melayu. Ia juga menyisipkan penjelasan tasawuf secara proporsional, terutama dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah, iman, dan akhlak. Misalnya, dalam QS. Al-Fatihah, ia menjelaskan makna rahman dan rahim tidak hanya secara leksikal, tetapi juga dari sudut pandang pengalaman spiritual sufi. Dengan demikian, tafsir ini menjadi gabungan antara ilmu zahir (syariat) dan ilmu batin (hakikat).
Salah satu ciri paling menonjol dari Tarjuman al-Mustafid adalah integrasi yang harmonis antara syariat dan tasawuf. Abdurrauf as-Singkili, sebagai tokoh sufi Syattariyah, meyakini bahwa perjalanan spiritual (suluk) harus berpijak pada Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam tafsirnya, ia sering menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an tidak hanya dari sisi hukum atau bahasa, tetapi juga dari dimensi batin (ma’na hakikat). Misalnya, dalam QS. Al-Baqarah [2]: 186 tentang doa, ia tidak hanya menjelaskan bentuk doa, tetapi juga hakikat kedekatan (qurb) dan pengalaman spiritual saat berdoa. Ia juga menekankan pentingnya nawaitu taqarrub ila Allah (niat mendekat kepada Allah) dalam setiap amal. Namun, ia tidak mengabaikan aspek syariat—fikih, ibadah, dan akhlak tetap menjadi fondasi. Pendekatannya ini menjadikan tafsirnya seimbang dan inklusif, sehingga bisa diterima oleh kalangan ulama, sufi, maupun masyarakat umum. Dalam konteks Nusantara, model seperti ini sangat penting karena mencegah dikotomi antara ulama “syariat” dan “sufi”, yang sering memicu konflik keagamaan.
Keberanian Abdurrauf as-Singkili menggunakan bahasa Melayu—bukan Arab—sebagai medium tafsir adalah langkah revolusioner dalam sejarah pemikiran Islam di Nusantara. Pada masa itu, bahasa Arab dianggap satu-satunya bahasa ilmu dan ibadah, sementara bahasa daerah dianggap tidak layak untuk urusan agama. Dengan menulis Tarjuman al-Mustafid dalam bahasa Melayu, ia mendemokratisasi akses terhadap Al-Qur’an, memungkinkan masyarakat awam, perempuan, dan anak-anak untuk memahami makna kitab suci. Bahasa yang digunakan bukan Melayu percakapan biasa, tetapi Melayu klasik yang indah, sistematis, dan sarat makna, sehingga menjadi model bagi karya-karya keagamaan selanjutnya. Karya ini turut berperan dalam pembentukan identitas intelektual Melayu-Islam, di mana bahasa Melayu tidak lagi inferior, tetapi menjadi wahana ilmu dan spiritualitas. Banyak ulama Nusantara setelahnya—seperti Syekh Yusuf al-Makassari, Tuanku Nan Tuo, dan Hamzah Fansuri—mengikuti jejaknya dalam menggunakan bahasa lokal untuk dakwah dan pendidikan.
Tarjuman al-Mustafid menjadi pionir tafsir berbahasa Melayu dan membuka jalan bagi perkembangan kajian Al-Qur’an di Nusantara. Karyanya menjadi rujukan utama dalam pesantren, surau, dan majelis taklim selama berabad-abad, terutama di Aceh, Sumatera, dan Semenanjung Melayu. Pengaruhnya terlihat pada karya-karya tafsir berikutnya, seperti Tafsir al-Mukhtasar karya Syekh Sulaiman ar-Rasuli, Tafsir al-Azhar karya Hamka, bahkan hingga tafsir modern berbahasa Indonesia. Selain itu, model integratif antara syariat dan tasawuf yang ia usung menjadi ciri khas tradisi Islam Nusantara, yang sering disebut sebagai Islam Nusantara—sebuah bentuk Islam yang moderat, inklusif, dan berakar pada budaya lokal. Bahkan hari ini, Tarjuman al-Mustafid masih digunakan dalam pengajian kitab, baik dalam bentuk manuskrip maupun cetakan modern oleh penerbit seperti Toha Putra, Al-Huda, dan Darul Ilmi. Warisannya membuktikan bahwa keilmuan Islam bisa tumbuh subur di tanah Nusantara, selama dilandasi kedalaman ilmu, kehati-hatian, dan komitmen terhadap dakwah yang kontekstual.
Tarjuman al-Mustafid bukan sekadar karya tafsir, melainkan mahakarya peradaban Islam Nusantara. Melalui karya ini, Abdurrauf as-Singkili berhasil membawa Al-Qur’an turun dari menara bahasa Arab ke ruang-ruang rumah, surau, dan hati masyarakat Melayu. Ia membuktikan bahwa keilmuan Islam tidak harus asing dari budaya lokal, selama tetap berpegang pada sumber otoritatif dan tujuan yang lurus. Dengan menggabungkan keilmuan Timur Tengah, spiritualitas sufi, dan bahasa Melayu, ia menciptakan model dakwah yang mendalam, mudah dipahami, dan berkelanjutan. Karyanya menjadi fondasi bagi perkembangan intelektual Islam di Indonesia, dan tetap relevan di era modern sebagai contoh bagaimana agama bisa menjadi pencerahan, bukan sekadar ritual. Di tengah tantangan globalisasi dan fragmentasi pemahaman agama, Tarjuman al-Mustafid mengingatkan kita bahwa Islam yang sejati adalah yang mengedepankan pemahaman, kasih sayang, dan keadilan—dari Aceh hingga seluruh Nusantara.
Rujukan
- Abdurrauf as-Singkili. Tarjuman al-Mustafid. Berbagai edisi cetak (Toha Putra, Al-Huda, Darul Ilmi).
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (1999). The Oldest Known Malay Manuscript: A 16th Century Malay Translation of the ‘Aqa’id al-Nasafi.
- Hooker, M. B. (Ed.). (1980). Adat and Islam: Essays on Religion and Law in Malaysia.
- Azra, Azyumardi. (2006). The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia.
- Noer, Deliar. (1980). Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942.
- Rahman, Fazlur. (1981). Major Themes of the Qur’an.
- Hasbullah. (2003). Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia.
- Muzaffar, Mohd. Fauzi. (2005). The Malay World and the Making of Islamic Knowledge.
- Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry. (2020). Studi Kritis atas Tafsir Tarjuman al-Mustafid.
- Komisi Nasional Kebudayaan Indonesia. (2018). Kearifan Lokal dan Tafsir Nusantara.