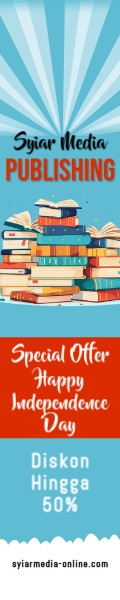1. Pendahuluan
Sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa thaharah (طهارة) merupakan fondasi utama yang mengawali seluruh rangkaian ibadah dalam Islam. Konsep ini tidak hanya dimaknai secara literal sebagai tindakan membersihkan diri dari najis dan hadas, tetapi juga mengandung dimensi spiritual yang sangat dalam sebagai persiapan untuk menghadap Allah SWT. Posisinya yang istimewa dalam syariat menjadikan thaharah sebagai mirror of faith (cermin keimanan), di mana kesucian lahiriah merupakan manifestasi dari kesucian batiniah.
Al-Qur’an secara tegas mengaitkan konsep kesucian dengan kecintaan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 222:
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri.”
Para mufassir klasik dan modern memberikan penekanan yang berlapis pada ayat ini. Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an menjelaskan bahwa kata al-mutathahhirin memiliki dua makna: (1) menyucikan diri dari hadas dan najis secara fisik, dan (2) menyucikan hati dari dosa dan akhlak yang tercela. Imam Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim juga menyatakan bahwa ayat ini adalah dalil yang jelas tentang keutamaan taubat dan kesucian, baik secara maknawi maupun hissi (fisik). Sementara itu, mufassir modern seperti Prof. Dr. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menegaskan bahwa thaharah adalah syarat fundamental bagi setiap ibadah, karena ibadah yang dilakukan dalam keadaan suci akan lebih membekas pada jiwa dan lebih mendekatkan diri kepada Allah.
Ruang lingkup thaharah dalam praktik sehari-hari sangatlah luas dan komprehensif, mencakup:
- Bersuci dari hadas, seperti wudhu untuk shalat dan mandi janabah setelah junub.
- Bersuci dari najis pada badan, pakaian, dan tempat.
- Bersuci secara simbolik sebagai solusi darurat, seperti tayammum ketika tidak ada air.
- Bersuci lingkungan, yang menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesehatan publik dan kebersihan ekosistem hidup.
Kesempurnaan thaharah sebagai bagian dari iman ditegaskan oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya:
الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ
“Kebersihan adalah separuh dari iman.” (HR. Muslim no. 223)
Imam An-Nawawi, dalam syarahnya terhadap Shahih Muslim, menjelaskan bahwa makna “separuh iman” ini memiliki dua penafsiran utama. Pertama, iman itu menghapuskan dosa, sementara thaharah juga menghapuskan dosa-dosa kecil, sehingga ia memiliki fungsi yang setara dengan separuh iman. Kedua, bahwa shalat—yang merupakan puncak manifestasi iman—tidak akan sah tanpa thaharah. Dengan demikian, thaharah menjadi penyempurna separuh ibadah yang paling utama. Dr. Mustafa Al-Bugha dalam Al-Fiqh Al-Manhaji ‘ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi’i menambahkan bahwa hadis ini juga menunjukkan keutamaan bersuci dalam Islam, yang nilainya setara dengan separuh keimanan karena menjadi prasyarat bagi sahnya berbagai ibadah mahdhah.
Kesimpulannya, thaharah bukan sekadar ritual mekanis pra-ibadah, melainkan sebuah disiplin spiritual yang menyeluruh. Ia adalah jembatan yang menghubungkan kesalehan individu dengan kesalehan sosial, dimana seorang Muslim yang bersih secara lahir dan batin tidak hanya mendekatkan diri kepada Tuhannya, tetapi juga turut menciptakan lingkungan yang sehat, harmonis, dan beradab. Dengan merujuk pada pendapat para ulama klasik dan modern, dapat disimpulkan bahwa thaharah adalah pilar iman yang argumentasinya kokoh, baik secara teologis maupun sosiologis.
Pentingnya Pendekatan Tafsir Tematik
Memahami konsep thaharah secara parsial dan terfragmentasi hanya akan menghasilkan pemahaman yang reduktif, yakni sekadar kumpulan aturan fiqih tentang wudhu, mandi, dan tayammum. Untuk mencapai pemahaman yang holistik dan komprehensif tentang kedudukan thaharah dalam worldview Islam, diperlukan sebuah pendekatan hermeneutika yang mampu menyatukan seluruh pesan Al-Qur’an yang tersebar. Di sinilah pendekatan tafsir tematik (التفسير الموضوعي) menempati posisinya sebagai metodologi yang tidak hanya efektif, tetapi juga penting dan argumentatif.
Pendekatan tafsir tematik, sebagaimana didefinisikan oleh para ulama ushul, adalah metode tafsir yang menghimpun semua ayat Al-Qur’an yang membahas satu tema tertentu—dalam hal ini thaharah—lalu menganalisisnya secara sinergis untuk mengungkap pandangan Al-Qur’an yang utuh tentang tema tersebut. Prof. Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi, seorang pionir dalam perumusan metodologi ini, dalam kitabnya Al-Bidayah fi Tafsir al-Maudhu’iy menegaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan kita untuk menyelami kedalaman makna suatu tema, melihat korelasi antara berbagai ayat, dan akhirnya merumuskan suatu teori Qur’ani yang menyeluruh.
Dalam konteks thaharah, pendekatan ini mengajak kita untuk tidak hanya berhenti pada ayat-ayat hukum yang eksplisit (seperti QS. Al-Maidah: 6 tentang wudhu), tetapi juga merangkainya dengan:
- Ayat-ayat tentang sifat Allah, seperti Al-Quddus (Maha Suci), yang menunjukkan bahwa kesucian adalah atribut Ilahi yang harus diupayakan oleh hamba-Nya.
- Ayat-ayat tentang penyucian jiwa (tazkiyatun nafs), seperti dalam QS. Asy-Syams: 9, “Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya.” Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin telah melihat hubungan simbiosis ini dengan sangat jelas. Beliau menyatakan bahwa menyucikan anggota badan lahiriah (seperti dalam wudhu) adalah cermin dan wasilah (sarana) untuk menyucikan anggota badan batiniah (hati) dari kotoran-kotoran dosa.
- Ayat-ayat tentang kebersihan lingkungan dan sosial, seperti perintah menyucikan pakaian (QS. Al-Muddatsir: 4) dan perintah menjauhi najis berhala dalam QS. Al-Hajj: 30. Mufassir modern seperti Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menafsirkan “najis” dalam konteks yang lebih luas, mencakup segala sesuatu yang kotor secara fisik dan moral, sehingga perintah thaharah juga bermuara pada terciptanya masyarakat yang bersih dan sehat.
Dengan merangkai semua ayat ini, tafsir tematik membuktikan bahwa thaharah adalah sebuah ajaran integral yang bersifat multi-dimensional, mencakup:
- Dimensi Ibadah Mahdhah: Sebagai syarat sah shalat.
- Dimensi Spiritual-Psikologis: Sebagai latihan disiplin diri dan pengingat akan kesucian yang Allah cintai.
- Dimensi Kesehatan: Menjaga kebersihan fisik dan lingkungan yang pada akhirnya mencegah penyakit.
- Dimensi Moral-Sosial: Membentuk pribadi yang disiplin, mencintai kebersihan, dan menghindari segala bentuk “kotoran” baik fisik maupun non-fisik seperti dosa dan maksiat.
Oleh karena itu, pendekatan tematik ini pada akhirnya mengukuhkan bahwa perintah thaharah sepenuhnya sejalan dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) yang dirumuskan oleh ulama seperti Imam Asy-Syathibi. Thaharah secara nyata memelihara lima hal fundamental: agama (melalui sahnya ibadah), jiwa (melalui hidup sehat), akal (dengan ketenangan jiwa), keturunan (dalam lingkungan yang bersih), dan harta (dengan mencegah pemborosan untuk pengobatan). Dengan demikian, melalui lensa tafsir tematik, thaharah benar-benar terungkap bukan sekadar sebagai syarat ibadah ritual, melainkan sebagai pilar fundamental peradaban Islami yang memadukan kesalehan individu dengan tanggung jawab sosial dan moral.
Tujuan Penulisan
Artikel ini disusun dengan beberapa tujuan strategis dan berlapis yang saling melengkapi, bertujuan untuk memberikan kontribusi pada khazanah pemikiran keislaman kontemporer, khususnya dalam memahami thaharah secara lebih mendalam dan kontekstual.
Pertama, tujuan utama penulisan ini adalah untuk melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi pemahaman tentang thaharah dengan menguraikan maknanya melalui perspektif Al-Qur’an yang komprehensif menggunakan pendekatan tafsir tematik. Hal ini penting untuk menggeser paradigma yang selama ini mungkin masih terbatas pada pemahaman fiqih yang bersifat legal-formal. Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam berbagai karyanya, pemahaman ayat-ayat ahkam (hukum) tidak boleh terlepas dari jiwa dan tujuan umum (maqashid) syariat. Dengan pendekatan ini, thaharah tidak lagi hanya dipandang sebagai “syarat sah shalat” semata, tetapi sebagai sebuah proses pendidikan jiwa yang berkelanjutan, yang menyucikan lahir dan batin, sebagaimana spirit yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah: 222.
Kedua, artikel ini bertujuan untuk menghimpun dan menganalisis secara kritis dalil-dalil normatif tentang thaharah, baik dari Al-Qur’an maupun Sunnah yang shahih, lalu menyajikannya dalam suatu kerangka yang sistematis dan mudah dipahami. Ini bukan sekadar enumerasi (penyebutan) dalil, tetapi upaya untuk menunjukkan koherensi (keterkaitan) antara satu dalil dengan dalil lainnya. Misalnya, menghubungkan perintah wudhu (QS. Al-Maidah: 6) dengan hadis tentang dosa-dosa yang gugur bersama air wudhu (HR. Muslim) dan ayat tentang penyucian jiwa (QS. Asy-Syams: 9). Dengan demikian, umat tidak hanya memiliki dasar yang kuat secara tekstual, tetapi juga memahami rasionalitas dan hikmah di balik setiap syariat thaharah, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pengamalan ibadah dari sekadar rutinitas menjadi ibadah yang penuh makna.
Ketiga, dan ini adalah tujuan yang sangat relevan, artikel ini bermaksud menegaskan relevansi dan aplikasi thaharah dalam konteks kehidupan modern. Di era yang dihadapkan pada tantangan global seperti pandemi, polusi, krisis sanitasi, dan degradasi moral, ajaran thaharah menawarkan solusi yang bersifat preventif dan kuratif. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam I’lam al-Muwaqqi’in telah mengisyaratkan bahwa dalam setiap syariat Islam terdapat hikmah medis. Thaharah dengan standar kebersihannya yang tinggi adalah buktinya. Dalam skala yang lebih luas, perintah menjaga kebersihan lingkungan—yang merupakan derivasi dari konsep thaharah—adalah respon Islam terhadap isu ekologi. Mufassir kontemporer seperti Dr. Abdul Majid An-Najar dalam karyanya Maqashid Asy-Syariah al-Bi’ah (Tujuan Syariat dalam Lingkungan) menyatakan bahwa banyak ayat thaharah mengandung pesan pelestarian lingkungan, seperti menjaga kebersihan air dan tanah.
Dengan demikian, melalui pemaparan yang argumentatif ini, artikel ini pada akhirnya bertujuan untuk memperkuat identitas keimanan seorang Muslim. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ, “Kebersihan adalah sebagian dari iman.” Memahami dan mengamalkan thaharah secara utuh berarti mempertebal iman dan sekaligus berkontribusi positif dalam membangun peradaban yang bersih, sehat, dan berakhlak mulia.
2. Definisi Thaharah secara Bahasa dan Istilah
Konsep thaharah memiliki landasan linguistik dan terminologis yang kokoh, yang memperkaya pemahaman kita tentang cakupan dan signifikansinya dalam Islam.
Secara bahasa, kata thaharah (طهارة) berasal dari akar kata thahara (طَهُرَ) – yathuru (يَطْهُرُ) yang mengandung makna dasar bersih, suci, murni, dan terbebas dari kotoran baik yang bersifat indrawi (hissiy) maupun maknawi (ma’nawiy). Pakar linguistik Arab klasik, Ibnu Manzhur, dalam karyanya yang monumental Lisan al-‘Arab, menjelaskan bahwa thaharah berarti an-nazafah (النظافة) yang berarti kebersihan, dan al-khalaw min al-‘uyub (الخَلَوُ من العيوب) yang berarti bebas dari cacat atau noda. Imam Al-Raghib al-Asfahani dalam Al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an menambahkan bahwa kata ini digunakan untuk dua bentuk kesucian:
- Kesucian Hissiyyah (حسية): Kesucian yang dapat dirasakan oleh indera, seperti bersihnya badan dari kotoran.
- Kesucian Ma’nawiyyah (معنوية): Kesucian yang bersifat non-fisik, seperti kesucian jiwa dari syirik dan dosa (qadr al-zullah wa al-rijs).
Dengan demikian, sejak dari akar katanya, thaharah telah membawa pesan ganda: pembersihan lahir dan batin.
Secara istilah (terminologi syariat), para ulama fikih mendefinisikan thaharah dengan definisi yang lebih teknis namun tetap selaras dengan makna bahasanya. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i mendefinisikannya sebagai: “Mengangkat (menghilangkan) status hadas yang menghalangi shalat, atau menghilangkan najis yang dapat dirasakan.”
Definisi ini mencakup dua aspek utama:
- Mengangkat Hadas (رفع الحدث): Hadas adalah kondisi ritual yang mencegah seseorang untuk melaksanakan ibadah tertentu. Ulama seperti Imam An-Nawawi dalam Raudhatut Thalibin membaginya menjadi:
- Hadas Kecil: Status yang diakibatkan oleh hal-hal seperti buang air kecil, buang air besar, atau tidur nyenyak, yang dihilangkan dengan berwudhu.
- Hadas Besar: Status yang diakibatkan oleh junub, haid, atau nifas, yang dihilangkan dengan mandi wajib (ghusl).
- Menghilangkan Najis (إزالة النجس): Najis adalah kotoran fisik yang secara spesifik diharamkan oleh syariat, seperti kencing, kotoran hewan, atau bangkai. Menghilangkannya dari badan, pakaian, atau tempat shalat disebut tathir (penyucian).
Dalil yang menjadi pijakan kewajiban ini sangat jelas dalam Al-Qur’an, salah satunya adalah firman Allah SWT:
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ
“Dan pakaianmu, maka sucikanlah.” (QS. Al-Muddatsir: 4)
Para mufassir memberikan penafsiran yang mendalam terhadap ayat ini. Imam Al-Qurthubi dalam Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an menyatakan bahwa perintah ini memiliki dua tafsiran:
- Tafsiran Lahiriah (Zhahiri): Menyucikan pakaian dari najis fisik yang dapat mencegah sahnya shalat.
- Tafsiran Bathiniyah (Maknawi): Menyucikan amal perbuatan dan akhlak dari segala dosa dan kemaksiatan, atau dalam tafsiran lain, menyucikan hati dari sifat-sifat tercela.
Syaikh Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar menekankan bahwa perintah ini, meskipun ditujukan kepada Nabi Muhammad ﷺ, mengandung pelajaran universal bagi umatnya. Beliau melihatnya sebagai fondasi bagi peradaban yang bersih; bahwa seorang Muslim harus memperhatikan kebersihan dirinya, dimulai dari hal yang paling dekat seperti pakaian, karena itu adalah cerminan dari jiwa yang bersih dan identitas keimanannya.
Oleh karena itu, definisi thaharah dalam istilah fikih bukanlah penyempitan makna, melainkan operasionalisasi spesifik dari makna bahasa yang luas. Ia adalah langkah pertama dan praktik nyata untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesucian jiwa (tazkiyatun nafs), sebagaimana diisyaratkan dalam berbagai ayat dan hadis.
Urgensi Thaharah dalam Kehidupan Muslim
Urgensi thaharah dalam Islam bersifat fundamental dan multidimensi, menembus batas antara ritual ibadah mahdhah dan praktik kehidupan sehari-hari. Posisinya yang sentral tidak dapat dipisahkan dari hakikat ibadah itu sendiri, khususnya shalat yang merupakan tiang agama (imad ad-din). Allah SWT menetapkan bersuci sebagai prasyarat mutlak keabsahan shalat, yang menegaskan bahwa jalan menuju Allah harus dimulai dengan kesucian. Sabda Rasulullah ﷺ menjadi landasan utama:
لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ
“Tidak diterima shalat tanpa bersuci.” (HR. Muslim no. 224)
Imam An-Nawawi, dalam syarahnya terhadap Shahih Muslim, menjelaskan bahwa hadis ini adalah dalil yang qath’i (pasti) tentang kewajiban thaharah untuk sahnya shalat. Beliau menegaskan bahwa thaharah adalah syarathu shihhah (syarat sah) shalat, bukan sekadar syarathu wujub (syarat wajib). Artinya, shalat yang dikerjakan tanpa thaharah adalah batal dan tertolak. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath al-Bari menambahkan bahwa penolakan ini berlaku baik secara hukum di dunia maupun secara spiritual di akhirat. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam QS. Al-Muddatsir: 4, yang memerintahkan penyucian pakaian—sebagai bagian dari thaharah—sebelum melaksanakan ibadah.
Lebih dari sekadar gerbang ibadah, thaharah adalah simbol penghambaan yang utuh. Seorang Muslim yang berwudhu atau mandi junub sebelum shalat sedang mempraktikkan kepatuhan total (kaffah) kepada perintah Tuhannya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin melihatnya sebagai tindakan yang mempersiapkan jiwa untuk khusyuk. Menyucikan anggota badan lahiriah, menurutnya, adalah pengingat dan wasilah untuk menyucikan anggota batiniah dari kelalaian dan dosa. Dengan demikian, thaharah menjadi jembatan yang menghubungkan kesucian lahir dan batin, memastikan bahwa seorang hamba menghadap Allah dalam keadaan yang paling layak, baik secara fisik maupun spiritual, yang sejalan dengan fitrah manusia yang cenderung pada kebersihan dan kesucian.
Di luar dimensi spiritual, thaharah membawa manfaat kesehatan yang nyata dan telah diakui secara medis. Ritual wudhu yang dilakukan berulang kali dalam sehari tidak hanya menyegarkan tubuh tetapi juga membersihkan bagian-bagian yang rentan menjadi sarang kuman, seperti mulut, hidung, dan kulit. Membasuh wajah dan anggota tubuh dapat mencegah penumpukan debu dan kotoran, mengurangi risiko penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan, dan konjungtivitis. Mandi janabah (ghusl) yang menyeluruh merupakan praktik detoksifikasi dan kebersihan kulit yang sangat efektif.
Ulama kontemporer seperti Dr. Abdul Basith Muhammad As-Sayyid dalam bukunya Al-I’jaz al-Ilmi fi al-Islam wa al-Sunnah al-Nabawiyyah (Mukjizat Ilmiah dalam Islam dan Sunnah Nabawiyah) menjelaskan bahwa gerakan wudhu merangsang titik-titik akupresur pada wajah dan tangan, meningkatkan sirkulasi darah, dan memberikan efek menenangkan pada sistem saraf. Dalam konteks modern, kebiasaan thaharah sangat relevan dengan prinsip pencegahan penyakit menular (preventive medicine). Praktik mencuci tangan dan membersihkan diri yang merupakan inti dari thaharah adalah garis pertahanan pertama dalam memutus mata rantai penularan penyakit, seperti yang terus diingatkan oleh para ahli kesehatan global.
Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa thaharah adalah ajaran paripurna yang memadukan ketundukan ritual dengan kebermanfaatan duniawi. Ia adalah bukti nyata bahwa syariat Islam selalu sejalan dengan kemaslahatan manusia (mashalih al-‘ibad), di mana setiap perintah ibadah mengandung hikmah yang dapat dirasakan baik untuk keselamatan akhirat maupun kesejahteraan hidup di dunia. Dengan memelihara thaharah, seorang Muslim tidak hanya menyempurnakan imannya tetapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang sehat, bersih, dan beradab.
Hubungan Thaharah dengan Iman dan Ibadah
Keterkaitan antara thaharah dengan iman dan ibadah bukan sekadar hubungan sebab-akibat yang bersifat legal-formal, melainkan sebuah relasi simbiosis yang bersifat ontologis dalam bangunan keislaman seorang Muslim. Iman yang hidup dan kokoh dalam hati akan secara otomatis mendorong seseorang untuk menjaga kesucian lahiriahnya, karena ia meyakini bahwa Allah Maha Indah dan mencintai keindahan serta kebersihan. Sebaliknya, kesungguhan dalam menjaga kesucian lahiriah akan memperkuat dan memantapkan iman di dalam hati. Relasi timbal balik ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an:
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah: 222)
Para mufassir klasik dan modern memberikan penafsiran yang mendalam tentang penyandingan dua kecintaan Allah dalam ayat ini. Imam Al-Qurthubi dalam Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an menyatakan bahwa kata al-mutathahhirin (orang-orang yang menyucikan diri) mencakup dua makna:
- Menyucikan diri dari hadas dan najis secara fisik sebagai syarat ibadah.
- Menyucikan diri dari perbuatan keji dan dosa serta membersihkan hati dari kotoran syirik dan kemunafikan.
Syaikh Muhammad Abduh dan Rasyid Rida dalam Tafsir Al-Manar menekankan bahwa penyandingan “taubat” dan “penyucian diri” menunjukkan bahwa kesempurnaan iman seorang hamba terwujud dengan menyucikan batin melalui taubat dan menyucikan lahir melalui thaharah. Dengan demikian, iman yang sempurna mustahil terwujud jika salah satunya diabaikan.
Lebih jauh, thaharah memiliki makna spiritual yang sangat dalam yang menjadikannya lebih dari sekadar ritual persiapan ibadah, tetapi juga sebagai ibadah itu sendiri yang memiliki nilai pembersihan dosa. Sabda Rasulullah ﷺ mengungkapkan realitas spiritual ini:
إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ
“Apabila seorang hamba Muslim berwudhu, maka dosa-dosanya keluar dari tubuhnya, hingga keluar dari bawah kuku-kukunya.” (HR. Muslim no. 245)
Imam An-Nawawi, dalam mensyarah hadis ini, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “dosa-dosa” di sini adalah dosa-dosa kecil. Beliau menegaskan bahwa wudhu menjadi sebab penghapusan dosa-dosa kecil selama dosa-dosa besar dihindari. Penjelasan serupa diberikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath al-Bari, yang menyatakan bahwa air wudhu yang mengalir menyentuh anggota tubuh menjadi kaffarah (penebus) bagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota tubuh tersebut.
Para ulama sufi dan ahli tasawuf seperti Imam Al-Ghazali memberikan dimensi pemahaman yang lebih dalam. Dalam Ihya’ Ulumuddin, beliau memaparkan bahwa setiap percikan air wudhu tidak hanya membersihkan kotoran fisik, tetapi juga “mendinginkan” anggota tubuh dari panasnya dosa dan maksiat yang pernah dilakukan. Setiap basuhan pada anggota wudhu merupakan simbol dari taubat dan komitmen untuk tidak mengulangi dosa dengan anggota tubuh tersebut di masa depan. Misalnya, membasuh tangan merupakan ikrar untuk tidak lagi menggunakan tangan untuk berbuat zalim.
Oleh karena itu, thaharah adalah manifestasi iman yang nyata dan jalan menuju penyucian jiwa yang berkelanjutan. Ia adalah bukti kesungguhan iman seseorang dan sekaligus sarana untuk meningkatkannya. Seorang Muslim yang khusyuk dalam berwudhu tidak hanya mendapatkan kesucian fisik untuk shalatnya, tetapi juga mengalami proses pemurnian spiritual yang mendekatkannya kepada Allah SWT, sehingga ia dapat menghadap Rabb-nya dengan hati yang lebih bersih dan tenang. Inilah hakikat dari sabda Nabi ﷺ bahwa “Kebersihan adalah sebagian dari iman.
3. Dalil-Dalil Thaharah dalam Al-Qur’an
Ayat tentang Wudhu (QS. Al-Maidah: 6)
Surah Al-Maidah ayat 6 merupakan landasan utama dan paling komprehensif dalam syariat thaharah, yang mengatur tiga bentuk penyucian: wudhu, mandi janabah (ghusl), dan tayammum. Ayat ini turun dengan gaya seruan yang penuh kasih, “Wahai orang-orang yang beriman!”, menunjukkan bahwa perintah ini adalah konsekuensi langsung dari keimanan mereka. Allah SWT berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, sapulah kepalamu, dan (basuhlah) kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Tetapi jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci); sapulah wajahmu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.” (QS. Al-Maidah: 6)
Para ulama tafsir dan fikih telah mengupas ayat ini secara mendalam. Imam Al-Qurthubi dalam Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an menyebut ayat ini sebagai “ayat wudhu yang agung” (ayat al-wudhu al-‘azhimah) yang menjadi induk dari semua pembahasan fikih tentang thaharah. Beliau menjelaskan bahwa perintah dimulai dengan niat (yang dipahami dari konteks) kemudian membasuh wajah, yang menjadi batasan awal dari basuhan.
Beberapa poin penting yang dikemukakan oleh para mufassir:
- Detail Rukun Wudhu: Ayat ini dengan tegas menyebutkan empat anggota wudhu yang harus dibasuh atau diusap. Perbedaan kata kerja antara fagsilu (membasuh) untuk wajah dan tangan, dengan wamsahu (mengusap) untuk kepala, menjadi dasar perbedaan hukum antara keduanya. Pembahasan tentang batasan “sampai siku” dan “mata kaki” menunjukkan sifatnya yang detail dan sempurna. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa mengusap kepala cukup dengan sebagian kepala, berdasarkan pemahaman terhadap huruf ba‘ dalam kata bi ru’usikum.
- Kewajiban Mandi Janabah: Perintah faiththahharu (maka hendaklah kamu menyucikan diri) untuk orang yang junub adalah perintah untuk mandi besar. Imam Asy-Syaukani dalam Fath al-Qadir menjelaskan bahwa mandi junub menghilangkan hadas besar dan mengembalikan seseorang pada keadaan suci.
- Keringanan Tayammum: Ayat ini merupakan contoh nyata dari keluwesan syariat Islam (taysir). Tayammum diizinkan dalam kondisi tertentu: sakit, safar, atau tidak menemukan air. Syaikh Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar menekankan bahwa kalimat “Allah tidak ingin menyulitkan kamu” adalah prinsip universal dalam Islam yang menghilangkan segala bentuk kesulitan dan kepayahan.
- Tujuan dan Hikmah: Penutup ayat, “Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur,” mengungkap maqashid (tujuan) dari syariat thaharah. Imam Ar-Razi dalam Mafatih al-Ghaib mengatakan bahwa tujuan “membersihkan kamu” mencakup pembersihan lahir dari kotoran dan batin dari dosa, sementara “menyempurnakan nikmat-Nya” adalah dengan memberikan petunjuk kepada syariat yang mudah dan membawa kemaslahatan.
Hadis Nabi ﷺ menguatkan dan merinci lebih lanjut tata cara yang disebutkan dalam ayat ini:
لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ
“Tidak diterima shalat tanpa bersuci.” (HR. Muslim no. 224)
Imam An-Nawawi dalam syarahnya menjelaskan bahwa hadis ini adalah dalil yang qath’i (pasti) bahwa thaharah adalah syarat sah shalat. Dengan demikian, wudhu yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah: 6 bukan hanya sekadar praktik kebersihan biasa, melainkan sebuah ibadah independen yang memiliki nilai spiritual tinggi dan menjadi kunci sahnya ibadah shalat, yang merupakan tiang agama. Ia adalah manifestasi dari ketaatan, ketundukan, dan syukur atas nikmat kesucian yang Allah anugerahkan.
Ayat tentang Tayammum (QS. An-Nisa’: 43)
Selain dalam QS. Al-Maidah, syariat tayammum juga dijelaskan oleh Allah SWT dalam Surah An-Nisa’ ayat 43, yang turut memperkaya pemahaman kita tentang fleksibilitas dan kemudahan dalam Islam.
وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا
“Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (QS. An-Nisa’: 43)
Para ulama tafsir, seperti Imam Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim, menjelaskan bahwa ayat ini turun sebelum ayat tayammum dalam Surah Al-Maidah dan mengandung beberapa pelajaran penting. Beliau menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan keluasan rahmat Allah dan keringanan (rukhsah) yang diberikan-Nya kepada hamba-hamba-Nya dalam kondisi tertentu.
Beberapa aspek penting yang dikemukakan para mufassir mengenai ayat ini:
- Sebab-Sebab Diperbolehkannya Tayammum: Ayat ini menyebutkan empat sebab yang membolehkan tayammum: sakit, safar, kembali dari buang air, dan menyentuh perempuan (jima’). Imam Al-Qurthubi dalam Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an menjelaskan bahwa “sakit” di sini mencakup kondisi di mana penggunaan air dikhawatirkan dapat memperparah penyakit atau menunda kesembuhan. Adapun “menyentuh perempuan” dipahami oleh mayoritas ulama sebagai kinayah (kiasan) untuk bersetubuh (jima’), yang menimbulkan hadas besar. Sebagian ulama lain memaknainya secara literal sebagai sentuhan kulit yang membatalkan wudhu.
- Makna Sha’idan Thayyiban (صَعِيدًا طَيِّبًا): Frase ini merupakan kunci dalam tayammum. Imam Ar-Razi dalam Mafatih al-Ghaib menafsirkan sha’id sebagai segala sesuatu yang berada di permukaan bumi, seperti debu, pasir, atau batu. Sementara thayyib berarti suci, murni, dan tidak terkontaminasi najis. Pemilihan kata ini menunjukkan bahwa media tayammum haruslah sesuatu yang suci dan berasal dari bumi, yang pada hakikatnya adalah sumber kesucian.
- Tata Cara yang Diperintahkan: Perintah famsahu (maka usaplah) wajah dan tangan menunjukkan bahwa tayammum menggantikan fungsi wudhu atau mandi, tetapi dengan cara yang berbeda—yaitu dengan mengusap, bukan membasuh. Imam Asy-Syaukani dalam Fath al-Qadir menyebutkan bahwa ulama sepakat tentang diusapkannya wajah, namun berbeda pendapat apakah “tangan” yang dimaksud termasuk sampai siku (seperti wudhu) atau hanya sampai pergelangan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang diusap adalah telapak tangan hingga pergelangan, berdasarkan hadis-hadis yang menjelaskan tata cara tayammum Nabi ﷺ.
- Penutup Ayat yang Penuh Kasih: Kalimat penutup, “Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun,” menurut Syaikh Abdurrahman As-Sa’di dalam Taysir al-Karim ar-Rahman, mengandung makna yang sangat dalam. Allah Maha Pemaaf (‘Afuwwun) terhadap kekurangan dalam pelaksanaan ibadah akibat uzur, dan Maha Pengampun (Ghafur) terhadap dosa-dosa yang mungkin terjadi karena ketidaktahuan atau keterpaksaan. Ini memberikan ketenangan bagi umat bahwa selama mereka berusaha memenuhi kewajiban sesuai kemampuannya, Allah akan menerima amal mereka.
Kemudahan ini ditegaskan kembali oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya:
جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا
“Bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan sarana bersuci (thahur).” (HR. Bukhari no. 335, Muslim no. 521)
Imam An-Nawawi dalam syarah Shahih Muslim menjelaskan bahwa makna thahur dalam hadis ini adalah segala yang dijadikan media untuk bersuci (debu/tanah), yang dapat digunakan untuk tayammum. Hadis ini menjadi dasar bahwa bumi secara keseluruhan adalah anugerah Allah yang memudahkan umat Islam untuk beribadah di mana pun mereka berada.
Dengan demikian, tayammum bukan sekadar pengganti darurat, tetapi simbol nyata dari rahmat, kemudahan, dan universalitas Islam. Ia menunjukkan bahwa syariat Islam memahami segala kondisi manusia, tidak memberatkan, dan selalu memberikan solusi. Tayammum adalah bukti bahwa kesucian dan hubungan dengan Allah dapat dijaga dalam segala keadaan, karena rahmat-Nya meliputi segala sesuatu.
Ayat tentang Kesucian Jiwa dan Hati
Pembahasan thaharah dalam Al-Qur’an mencapai puncaknya ketika menyentuh dimensi yang paling esensial, yaitu penyucian jiwa (tazkiyatun nafs) dan hati (qalb). Thaharah fisik adalah pintu gerbang menuju pembersihan yang lebih dalam dan fundamental ini. Allah SWT berfirman dalam Surah Asy-Syams:
قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا
“Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya.” (QS. Asy-Syams: 9-10)
Ayat ini menempatkan penyucian jiwa sebagai penentu utama keberuntungan abadi dan kerugian hakiki. Para mufassir memberikan penjelasan yang mendalam tentang makna “menyucikan” dan “mengotori” jiwa.
Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin membedakan dua makna tazkiyah:
- Tazkiyah atas dasar usaha hamba: Yaitu menyucikan jiwa dari akhlak yang tercela dan kotoran-kotoran dosa, serta menghiasinya dengan akhlak yang mulia. Inilah yang dimaksud dengan “menyucikan jiwanya”.
- Tazkiyah atas dasar pemberian Allah: Yaitu tumbuhnya jiwa dan bertambahnya kebaikan serta cahaya ilahi di dalamnya.
Imam Ar-Razi dalam Mafatih al-Ghaib menafsirkan bahwa “menyucikan jiwa” berarti membersihkannya dari syirik, kufur, nifaq, dan segala akhlak yang buruk. Sementara “mengotorinya” berarti mengisinya dengan kekejian dan kemaksiatan. Beliau menegaskan bahwa kesucian jiwa inilah yang menjadi tujuan akhir semua ibadah lahiriah.
Syaikh Abdurrahman As-Sa’di dalam Taysir al-Karim ar-Rahman menjelaskan bahwa keuntungan (al-falah) yang dijanjikan mencakup semua kebaikan dunia dan akhirat, sementara kerugian (al-khab) mencakup semua keburukan. Dengan demikian, kesucian jiwa bukanlah sebuah pilihan, melainkan prasyarat untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan sejati.
Konsep ini diperkuat secara gamblang oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya yang agung:
أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ
“Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh baik; jika ia rusak, maka seluruh tubuh rusak. Ketahuilah, ia adalah hati.” (HR. Bukhari no. 52, Muslim no. 1599)
Imam An-Nawawi, dalam syarah Shahih Muslim, menjelaskan bahwa “seluruh tubuh” yang dimaksud mencakup perbuatan anggota badan lahiriah. Hati adalah raja yang mengendalikan seluruh pasukannya (anggota tubuh). Jika sang raja baik—dengan iman, takwa, dan ikhlas—maka seluruh perbuatan anggota tubuh akan menjadi baik dan bernilai ibadah. Sebaliknya, jika sang raja rusak—dipenuhi syirik, riya’, dengki, dan penyakit hati lainnya—maka seluruh perbuatan lahiriah, sekalipun terlihat baik, akan menjadi rusak dan tertolak di sisi Allah.
Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath al-Bari menambahkan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan membersihkan hati dan terus-menerus memantau serta memperbaikinya, karena ia adalah fondasi dari segala sesuatu.
Oleh karena itu, thaharah batiniah—menyucikan hati dari syirik, riya’, ujub, hasad, dan segala penyakit—adalah inti dan ruh dari seluruh thaharah. Seorang Muslim yang menjaga kebersihan hatinya akan lebih mudah mendekat kepada Allah, menjalankan ibadah dengan ikhlas, dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap geraknya. Ibadah thaharah fisik seperti wudhu, mandi, dan tayammum adalah latihan dan wasilah (sarana) untuk mencapai tujuan tertinggi ini: hati yang bersih dan selamat (qalbun salim).
Dengan demikian, thaharah dalam Islam adalah sebuah perjalanan yang dimulai dari menyucikan yang lahir untuk sampai kepada menyucikan yang batin, menyucikan tubuh untuk membersihkan hati, dan pada akhirnya, menyucikan seluruh kehidupan seorang Muslim untuk menghadap Allah SWT.
Analisis Tematik terhadap Ayat-Ayat Thaharah
Melalui pendekatan tematik (tafsir maudhu’i), seluruh ayat-ayat Al-Qur’an tentang thaharah dapat dianalisis untuk mengungkap sebuah bangunan konsep yang utuh, koheren, dan multidimensi. Analisis ini mengelompokkan dan mensintesiskan berbagai ayat tersebut ke dalam dua poros utama yang saling melengkapi:
- Thaharah Hissiyah (حسية) atau Lahiriah:Ini adalah dimensi fisik-ritual yang terlihat dan terukur. Ayat-ayat dalam kelompok ini memberikan petunjuk operasional yang jelas.
- QS. Al-Maidah: 6: Merupakan fondasi utama yang mengatur tata cara bersuci dari hadas, baik kecil (dengan wudhu) maupun besar (dengan mandi), serta alternatifnya (tayammum).
- QS. Al-Muddatsir: 4: Perintah menyucikan pakaian, yang termasuk dalam kategori menghilangkan najis (izalah al-khabats).
- QS. Al-Baqarah: 222: Ayat ini, meskipun berbicara dalam konteks haid, mengandung prinsip universal tentang kecintaan Allah pada orang-orang yang menyucikan diri, yang mencakup penyucian fisik.
- QS. Al-Anfal: 11: Ayat tentang turunnya air hujan untuk menyucikan manusia, menegaskan air sebagai media utama thaharah hissiyah.
- Thaharah Ma’nawiyah (معنوية) atau Batiniah:Ini adalah dimensi moral-spiritual yang bersifat abstrak namun menjadi tujuan esensial.
- QS. Asy-Syams: 9-10: Ayat tentang penyucian jiwa (tazkiyatun nafs) sebagai kunci keberuntungan.
- QS. Asy-Syams: 9-10: Ayat tentang penyucian jiwa (tazkiyatun nafs) sebagai kunci keberuntungan.
- QS. Al-Baqarah: 222: Kecintaan Allah pada al-mutathahhirin juga mencakup mereka yang menyucikan hati.
- QS. At-Taubah: 108: Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri, yang dalam konteks ayat ini terkait dengan menyucikan hati dan tempat ibadah.
Simpulan Analisis Tematik: Sebuah Kesatuan yang Tak Terpisahkan
Analisis tematik terhadap seluruh ayat ini menegaskan bahwa kedua dimensi thaharah—lahiriah dan batiniah—bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan sebuah kesatuan yang integral dan saling bergantung dalam membentuk pribadi Muslim yang kaffah.
Pandangan para ulama memperkuat kesimpulan ini:
- Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin menggambarkan hubungan ini bagai dua sisi mata uang. Thaharah hissiyah (seperti wudhu) adalah syakl (bentuk luar) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ma’na (makna batin) yaitu thaharah qalbiyah. Menurutnya, menyucikan anggota tubuh lahir adalah simbol dan wasilah untuk menyucikan anggota batin dari dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh tersebut.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam Miftah Dar as-Sa’adah menyatakan bahwa syariat selalu menyertakan hikmah. Hikmah dari disyariatkannya thaharah lahiriah adalah untuk melatih dan menyiapkan jiwa agar terbiasa dengan kebersihan, yang pada akhirnya akan memudahkannya untuk mencapai kebersihan batin. Seseorang tidak mungkin mencapai kesucian hati yang sempurna sambil mengabaikan kesucian fisiknya.
- Syaikh Muhammad Abduh menekankan bahwa pengabaian terhadap salah satu dimensi akan menyebabkan ketidakseimbangan. Seorang yang suci lahiriah tetapi kotor batinnya diibaratkan oleh para ulama sebagai “kuburan yang dihalusi”, indah di luar tetapi kosong dan penuh tulang belulang di dalam. Sebaliknya, mengklaim suci batin tetapi mengabaikan thaharah hissiyah adalah kontradiksi, karena ketundukan pada syariat lahiriah adalah bukti nyata dari kesucian batin.
Oleh karena itu, analisis tematik ini membawa pada kesimpulan yang tegas: Thaharah dalam Islam adalah sebuah konsep holistik yang mencakup kesucian lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial. Seorang Muslim yang hakiki adalah dia yang menyeimbangkan kedua aspek ini; menjaga wudhu dan kebersihan fisiknya dengan disiplin, seraya terus-menerus berjihad untuk membersihkan hatinya dari segala penyakit yang merusak. Inilah thaharah yang sebenarnya, yang menjadi cermin dari iman yang hidup dan diterima oleh Allah SWT.
4. Jenis-Jenis Thaharah Menurut Al-Qur’an
Thaharah Hissiyah (Bersuci Fisik)
Thaharah hissiyah (الطهارة الحسية) merujuk pada tindakan bersuci yang bersifat indrawi dan fisik, yang melibatkan penghilangan najis (najasah) dan pengangkatan status hadas (hadath) dari badan, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk ibadah. Jenis thaharah ini merupakan fondasi praktis yang memungkinkan dilaksanakannya berbagai ibadah mahdhah, terutama shalat.
Allah SWT berfirman:
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ
“Dan pakaianmu, maka sucikanlah.” (QS. Al-Muddatsir: 4)
Para mufassir menekankan bahwa perintah dalam ayat ini, meskipun ditujukan kepada Nabi Muhammad ﷺ, bersifat universal bagi seluruh umat Islam. Imam Al-Qurthubi dalam Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an menjelaskan bahwa perintah ini mencakup dua aspek:
- Penyucian Lahiriah: Menjaga pakaian dari najis fisik yang dapat mencegah sahnya shalat.
- Penyucian Maknawi: Menyucikan amal perbuatan dari dosa dan kemaksiatan, atau menyucikan hati dari sifat-sifat tercela. Imam Al-Baghawi dalam Tafsir Al-Baghawi juga menyebutkan pendapat bahwa yang dimaksud adalah menyucikan pakaian dari segala kekotoran dan perbuatan dosa.
Ruang Lingkup Thaharah Hissiyah meliputi:
- Mengangkat Hadas (رفع الحدث): Yaitu mengembalikan status ritual seseorang menjadi suci setelah terkena hadas kecil atau besar.
- Hadas Kecil: Diangkat dengan berwudhu, sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Maidah: 6.
- Hadas Besar: Diangkat dengan mandi wajib (ghusl), juga berdasarkan QS. Al-Maidah: 6.
- Menghilangkan Najis (إزالة النجاسة): Yaitu membersihkan benda-benda najis dari badan, pakaian, dan tempat shalat. Ini didasarkan pada ayat-ayat seperti QS. Al-Muddatsir: 4 dan juga hadis-hadis Nabi yang menjelaskan jenis-jenis najis dan cara mensucikannya.
- Tayammum (التيمم): Sebagai pengganti air ketika tidak tersedia atau tidak dapat digunakan, berdasarkan QS. Al-Maidah: 6 dan QS. An-Nisa’: 43. Imam Asy-Syaukani dalam Nail al-Authar menegaskan bahwa tayammum adalah bukti nyata kemudahan dalam syariat Islam dan merupakan bentuk thaharah hissiyah yang sah.
Dimensi Spiritual Thaharah Hissiyah:
Meskipun bersifat fisik, thaharah hissiyah memiliki dampak dan makna spiritual yang sangat dalam. Rasulullah ﷺ bersabda:
إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ
“Apabila seorang hamba Muslim berwudhu, maka dosa-dosanya keluar dari tubuhnya, hingga keluar dari bawah kuku-kukunya.” (HR. Muslim no. 245)
Para ulama menjelaskan makna spiritual dari hadis ini:
- Imam An-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menyatakan bahwa yang dimaksud “dosa-dosa” di sini adalah dosa-dosa kecil. Wudhu berfungsi sebagai kaffarah (penebus) bagi dosa-dosa kecil tersebut.
- Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin memberikan penafsiran yang lebih simbolis. Beliau melihat setiap percikan air wudhu yang membersihkan anggota tubuh sebagai pembersih dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh tersebut. Membasuh mulut membersihkan dosa-dosa lisan, membasuh tangan membersihkan dosa-dosa yang dilakukan tangan, dan seterusnya. Ini menjadikan wudhu tidak hanya sebagai tindakan fisik, tetapi juga sebagai proses introspeksi dan pembersihan moral yang berkelanjutan.
Dengan demikian, thaharah hissiyah adalah perpaduan sempurna antara kepatuhan ritual dan penyucian spiritual. Ia adalah tindakan fisik yang disyariatkan untuk mempersiapkan seorang hamba menghadap Allah dalam keadaan yang paling layak, sekaligus menjadi sarana untuk menghapus kesalahan-kesalahan kecil dan menyadarkan diri akan pentingnya menjaga kesucian lahir dan batin secara terus-menerus.
Thaharah Ma’nawiyah (Bersuci Spiritual)
Thaharah ma’nawiyah (الطهارة المعنوية) merupakan puncak dan tujuan esensial dari seluruh proses pensyariatan thaharah dalam Islam. Ia adalah penyucian jiwa (tazkiyatun nafs) dan hati (qalb) dari segala penyakit batin (amradh al-qulub) seperti syirik, riya’, ujub, hasad (dengki), dendam, sombong, dan cinta dunia yang berlebihan. Jika thaharah hissiyah membersihkan “wadah”, maka thaharah ma’nawiyah membersihkan “isi”nya.
Allah SWT menegaskan keutamaan hati yang bersih dalam firman-Nya:
يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
“(Yaitu) pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih (selamat).” (QS. Asy-Syu’ara’: 88-89)
Para ulama tafsir memberikan penjelasan mendalam tentang makna qalbun salim (hati yang selamat). Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin mendefinisikannya sebagai hati yang terbebas dari segala syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah dan dari segala syubhat yang menyimpang dari kebenaran. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa qalbun salim adalah hati yang bersih dari syirik dan keragu-raguan, serta hanya mengesakan Allah. Syaikh Abdurrahman As-Sa’di menambahkan bahwa ia adalah hati yang selamat dari segala penyakit yang menyebabkan penyimpangan dan kehancuran.
Metode Penyucian Jiwa (Tazkiyatun Nafs):
Pencapaian thaharah ma’nawiyah bukanlah proses yang instan, melainkan perjalanan spiritual yang memerlukan kesungguhan (mujahadah) yang terus-menerus. Para ulama, seperti Imam Ibnul Qayyim dalam Madarij as-Salikin, merumuskan metode-metodenya:
- At-Taubat an-Nasuh (Taubat yang Sungguh-sungguh): Ini adalah langkah pertama dan fondasi utama. Taubat yang sebenarnya adalah membersihkan noda dosa dengan penyesalan, meninggalkan maksiat, dan bertekad untuk tidak mengulanginya.
- Al-Muhasabah (Introspeksi Diri): Seorang Muslim harus terus-menerus mengoreksi dirinya sendiri sebelum dihisab di akhirat, sebagaimana nasihat Umar bin Khattab RA: “Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab.”
- Al-Muraqabah (Merasa Selalu Diawasi Allah): Merasakan kehadiran dan pengawasan Allah dalam setiap keadaan, yang akan mencegah diri dari berbuat maksiat.
- Dzikrullah (Mengingat Allah): Hati yang selalu dipenuhi dengan dzikir kepada Allah akan menjadi tenang, bersih, dan terjaga dari kelalaian. Allah berfirman, “Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram.” (QS. Ar-Ra’d: 28)
- Tilawah dan Tadabbur Al-Qur’an: Al-Qur’an berfungsi sebagai obat (syifa) bagi penyakit-penyakit hati. Membacanya dengan merenungi maknanya akan membersihkan hati dari kotoran syubhat dan syahwat.
- Melakukan Amal Saleh dengan Ikhlas: Ibadah dan amal saleh yang dilakukan semata-mata karena Allah (lillah) dan sesuai dengan tuntunan Nabi (‘ala sunnah) akan memancarkan cahaya dan kesucian dalam hati.
Hubungan Simbiosis dengan Thaharah Hissiyah:
Thaharah ma’nawiyah dan hissiyah memiliki hubungan yang simbiosis dan tidak terpisahkan. Imam Al-Ghazali menganalogikan hubungan ini seperti sebuah cermin. Thaharah hissiyah membersihkan cermin lahiriah (anggota tubuh), sementara thaharah ma’nawiyah membersihkan cermin batiniah (hati). Cermin lahiriah yang bersih memudahkan cermin batin untuk memantulkan cahaya kebenaran, dan sebaliknya, cermin batin yang bersih akan memberikan makna dan ruh pada setiap tindakan lahiriah.
Oleh karena itu, tanpa thaharah batiniah, ibadah lahiriah—sekalipun dilakukan dengan sempurna secara teknis—akan kehilangan ruh dan nilainya di sisi Allah. Ia bagaikan jasad tanpa nyawa, atau seperti bangunan yang megah tetapi rapuh fondasinya. Sebaliknya, klaim memiliki kesucian batin tetapi mengabaikan kesucian lahiriah adalah suatu kontradiksi dan pengingkaran terhadap perintah Allah yang jelas.
Dengan demikian, thaharah ma’nawiyah adalah jiwa dari seluruh amalan Islam. Ia adalah tujuan akhir yang menjamin keselamatan di akhirat dan memberikan makna yang dalam bagi setiap ritus ibadah yang dilakukan seorang Muslim. Kesucian hati inilah yang akan membuat thaharah hissiyah, shalat, puasa, dan seluruh amal saleh lainnya diterima dan bernilai di hadapan Allah SWT.
Keterkaitan Thaharah Lahir dan Batin: Sebuah Simbiosis yang Sempurna
Analisis terhadap ayat-ayat dan hadis tentang thaharah mengungkap suatu hubungan yang bukan sekadar tambahan, melainkan simbiosis mutualistik yang mendalam antara thaharah lahiriah (hissiyah) dan thaharah batiniah (ma’nawiyah). Keduanya bagaikan dua sisi dari satu koin yang sama, atau seperti jasad dan ruh yang tidak dapat dipisahkan.
- Thaharah Lahiriah sebagai Syarat Sah, Thaharah Batiniah sebagai Syarat Diterima
Para ulama klasik telah merumuskan dengan sangat jelas perbedaan mendasar ini. Imam Al-Ghazalidalam Ihya’ Ulumuddinmenjelaskan bahwa setiap ibadah memiliki dua rukun: lahiriah (zahir) dan batiniah (batin). Thaharah hissiyah (seperti wudhu) adalah syarat sah (shartu shihhah) bagi ibadah lahiriah, seperti shalat. Sementara itu, thaharah ma’nawiyah (seperti ikhlas dan terbebas dari riya’) adalah syarat diterimanya (shartu qubul) ibadah tersebut di sisi Allah.
- Tanpa thaharah hissiyah, shalat secara hukum syariat tidak sah dan tidak menggugurkan kewajiban. Ini berdasarkan hadis, “Tidak diterima shalat tanpa bersuci.” (HR. Muslim).
- Tanpa thaharah ma’nawiyah, shalat mungkin sah secara formal dan menggugurkan kewajiban, tetapi ia kehilangan nilainya di hadapan Allah. Ia menjadi amal yang sia-sia, sebagaimana ancaman dalam firman-Nya, “Maka celakalah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, yang berbuat riya.” (QS. Al-Ma’un: 4-6).
- Lahiriah sebagai Cermin dan Wasilah bagi Batiniah
Thaharah hissiyah tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki dimensi pedagogis (pendidikan) dan psikologis. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyahdalam Miftah Dar as-Sa’adahmenyatakan bahwa syariat-syariat lahiriah ditetapkan untuk membentuk dan mempengaruhi kondisi batin. Gerakan membasuh anggota tubuh dalam wudhu adalah simbol dari tekad untuk tidak menggunakan anggota tubuh tersebut untuk bermaksiat. Dengan demikian, thaharah lahiriah berfungsi sebagai latihan repetitif (riyadhah) untuk menyucikan jiwa dan mengingatkan hati akan pentingnya kebersihan dari dosa. - Batiniah sebagai Pemberi Makna dan Ruh bagi Lahiriah
Sebaliknya, thaharah ma’nawiyah adalah unsur yang memberikan kehidupan dan keikhlasan pada tindakan lahiriah. Seorang yang berwudhu dengan khusyuk dan kesadaran penuh akan makna spiritualnya, sangat berbeda dengan orang yang berwudhu sekadar membasuh anggota badan. Yang pertama menggabungkan kesucian lahir dan batin, sementara yang kedua hanya mendapatkan kesucian lahir saja. Imam An-Nawawidalam syarah Shahih Muslim menekankan pentingnya hadhir al-qalb(kehadiran hati) dan merenungi makna dalam setiap ibadah, termasuk thaharah.
Kesimpulan: Keseimbangan yang Menghasilkan Keutuhan
Oleh karena itu, Islam menekankan keseimbangan yang utuh antara kedua aspek ini. Seorang Muslim yang ideal adalah dia yang:
- Disiplin dalam thaharah hissiyah: Cermat dalam menjaga wudhu, mandi janabah, membersihkan pakaian dan tempat dari najis, karena itu adalah perintah Allah yang jelas.
- Sungguh-sungguh dalam thaharah ma’nawiyah: Terus-menerus berjihad membersihkan hatinya dari syirik, riya’, dengki, dan akhlak tercela lainnya, karena itu adalah tujuan akhir dari penciptaannya.
Keterkaitan ini digambarkan dengan sempurna dalam firman Allah:
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri.” (QS. Al-Baqarah: 222)
Para mufassir seperti Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa “orang-orang yang bertaubat” merujuk pada mereka yang menyucikan batinnya dari dosa, sementara “orang-orang yang menyucikan diri” mencakup mereka yang menyucikan lahiriahnya dari hadas dan najis. Penyandingan kedua kecintaan Allah ini menegaskan bahwa ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah adalah yang lahir dari kesucian lahir dan batin yang menyatu secara harmonis. Inilah kesempurnaan Islam yang memadukan antara syariat dan hakikat, antara bentuk dan makna, antara jasad dan ruh.